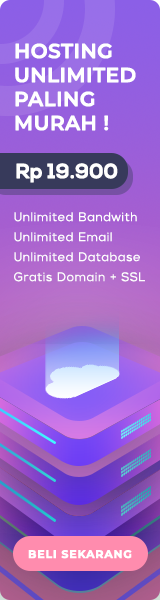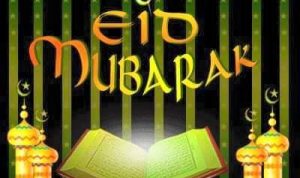BERBAGI News –Dua kamar di lantai dua kediaman dr Willem berjendela menghadap Sungai Jangkok. Sekali waktu Cornelia duduk di salah satu kamar. Ia buka jendela. Udara segar memasuki ruangan. Gadis itu memandang air sungai yang mengalir menuju muara di arah barat melintasi Kampung Banjar. Airnya jernih, tidak terlalu dalam. Anak-anak sering mandi di situ. Di bawah jembatan sepanjang hari selalu ada orang datang memancing ikan. Cornelia begitu girang ketika melihat ikan berhasil dikail. Mujair sebesar telapak tangan, lele, atau ikan gabus. Mereka selalu pulang membawa ikan. Tangkapan itu mereka masukkan ke dalam keranjang dari kulit bambu.
Siang itu ia mengajak Rabiyah naik. Mereka bercakap-cakap sambil menikmati singkong goreng dan teh manis.
Sambil memendekkan kuku-kuku jari tangan saudara majikannya, Rabiyah menceritakan nasib perkawinan demi perkawinannya yang gagal.
Walau sudah berkali-kali menikah, perempuan itu tak memiliki anak. Setelah bersuami untuk ketiga kalinya dan belum juga dikaruniai anak, ia memastikan dirinya seorang wanita mandul. Faktor tak bisa memberikan keturunan inilah menjadi penyebab perceraian dengan ketiga suaminya.
“Kalau saya dapat anak dari awal perkawinan dulu, usianya sekarang tak jauh dengan Non Lia,” katanya.
Rabiyah wanita berwajah cukup manis. Kulitnya coklat cerah. Silsilahnya dari sebuah desa di Lombok Tengah. Karena cukup lama bekerja di rumah keluarga-keluarga Belanda ia cukup paham berbahasa Belanda.
“Non, lima tahun lalu ada orang Belanda ingin mengajak saya menikah. Tapi saya tidak mau. Walaupun saya akan diajak pulang ke rumahnya di Belanda.”
“Kenapa tidak mau?”
“Dia tua, Non. Umurnya enam puluh tahun lebih.”
“Kenapa kalau tua?”
“Itunya Non, apa masih kuat?” kata Rabiyah sambil menunjuk selangkangannya.
Tawa Cornelia berderai di siang itu. Suara tawa yang renyah, tawa lepas, tanpa beban.
“Inaq, ajari saya bahasa Sasak.”
“Untuk apa? Kalau orang bisa bahasa Belanda, gampang diterima bekerja di mana-mana. Nah, bahasa Sasak?”
“Saya ingin bisa bercakap-cakap dengan siapa saja warga pribumi. Juga dengan anak-anak. Saya menyukai anak-anak. Tapi setiap saya mencoba dekati, mereka lari.”
“Non Lia bisa pelajari kapan saja.”
“Mulai besok, ya?”
“Nggih, Non.”
“Nggih?”
“Nggih dan aok artinya iya. Tapi nggih lebih sopan, waktu berbicara dengan orang yang dihormati atau lebih tua. Begrijp je, mooi meisje?”
“Nggih, Inaq.”
Keduanya tertawa.
“Inaq.”
“Mulai sekarang Inaq jangan bersimpuh lagi di depan saya.”
“Kenapa, Non? Saya ini babu. Non Lia majikan saya. Semua babu memang harus begitu untuk menghormati majikan.”
“Inaq bukan babu saya.”
Rabiyah mengangkat wajahnya.
“Non Lia bilang saya bukan babu? Non mau memberhentikan saya?”
Cornelia tersentak mendengar pertanyaan Rabiyah. Ia merapatkan tubuhnya ke dekat wanita pribumi itu.
“Memang bukan babu saya. Tapi inaq saya. Ibu saya.”
Mendengar itu Rabiyah tak kuasa membendung air matanya.
“Saya kehilangan ibu sejak kecil. Inaq tak punya anak. Ya anggap saya anak inaq,” katanya tersenyum. Ia hapus air mata Rabiyah dengan jari-jemarinya yang lentik. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)