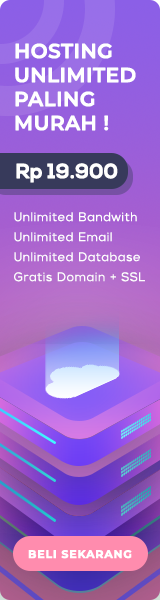Kadal nongak leq kesambiq
Benang kataq setakilan
Aduh dende
Te ajah onyak ndek ne matiq
Payu salaq kejarian
Aduh dende
Mun cempake siq kembang sandat
Saq sengake jari sahabat
Aduh dende
Dengan fasih tembang Sasak purba itu dinyanyikan Cornelia. Saat ia mengulang kembali, terdengar pintu kamar Willem dibuka.
“Hai, kau bisa lagu Lombok, siapa ajari? Ha ha ha!”
“Inaq.”
“Oya, lupa. Tadi ada datang surat untukmu. Satunya dari ayah. Sepucuk lagi aku tak kenal pengirimnya,” Willem melangkah ke kamar praktik.
Cornelia membuka sampul surat pertama. Surat ayahnya.
Anakku tersayang, Cornelia Doutzen.
Ayah tak berada di Batavia lagi, ketika surat ini tiba. Ayah dan ibumu memutuskan berangkat ke Britania. Di Batavia, ayah merasakan ironi. Di negeri ini kita menjadi bagian sebuah praktik penindasan selama ratusan tahun. Bangsa kita sebagai penjajah yang ditakuti pribumi, dianggap bangsa hebat. Tetapi negeri kita sendiri sudah dirampas bangsa yang lebih kuat. Pasca pengeboman di Rotterdam, kita kocar-kacir. Seluruh kota kebanggaan kita telah jatuh, dikuasai Jerman. Bukankah ini sesuatu yang tak lucu? Belanda negara penjajah, tapi negerinya sendiri dijajah.
Holokaus, genosida terbesar dan terkejam sepanjang sejarah. Enam juta penganut Yahudi di Eropa dibantai Nazi Jerman. Lima juta orang dewasa, dan satu juta anak-anak telah tamat riwayatnya. Lebih dari 70 persen warga Yahudi di negeri kita dikirim ke kamp konsentrasi.
Cornelia, di negeri jajahan Belanda ini ayah merasa serba salah. Di sini mungkin lebih tenteram, tetapi tidak ada jaminan situasi tetap stabil.
Jepang telah memulai Perang Asia Pasifik atau dikenal dengan Perang Asia Timur Raya yang sekaligus mengawali perang dunia II. Negeri monarki di Asia yang baru mengawali sejarah invasi. Dengan kemenangan di Perang Dunia I bersama pihak sekutu, Jepang dengan kekuatan militer dunia berusaha memperluas pengaruh di Asia. Inilah yang ayah khawatirkan. Dua benua besar, Asia dan Eropa, tak bisa terhindar dari kekacauan yang ditimbulkan perang.
Ayah berharap, semoga di pulau kecil tempatmu bersama Willem, kalian tetap aman. Tapi ayah berpesan agar kalian selalu tetap berhati-hati.
Ayah merindukanmu. Merindukan Willem. Kita bercerai-berai lantaran satu keadaan, kekuatan besar, yang tak bisa kita lawan. Semoga di suatu waktu, kita bisa kembali pulang ke negeri kita. Negeri yang paling indah.
Ayahmu, Lubbers de Hoffman.
Lama Cornelia termenung. Wajah ayahnya terbayang. Tiba-tiba ia sangat merindukannya.
“Ayah,” bisiknya. Air matanya menggenang.
Ia memandang surat kedua dengan tiada minat. Tapi ia buka juga.
Cornelia sayang, kembang Rotterdam.
Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Bahkan saat aku tengah membidik tubuh ekstremis-ekstremis itu, wajahmu tak pernah hilang.
Aku banyak punya cerita untukmu. Dua hari lalu peluru senapanku menembus kepala seorang gembong pengacau di pinggir kota. Otaknya berhamburan.
Mengapa kau meninggalkan Batavia? Di sana tempat ramai, banyak tempat untuk kita bersenang-senang. Apa yang kau cari di Lombok? Kau pasti menderita di sana. Aku akan menjemputmu. Sebulan lagi aku dapat cuti.
Peluk rindu untukmu. Graaf Maarten.
“Bajingan! Dipikirnya aku suka mendengar cerita-ceritanya selama ini,” Cornelia menghentakkan kakinya ke lantai. Surat itu dilemparnya di atas meja.
“Willem, Willem!”
Dokter itu keluar dari kamarnya. “Ada apa, Cornelia?”
“Brengsek itu akan menyusulku.”
“Siapa?”
“Graaf, serdadu yang sering ke rumah paman. Aku selalu terpaksa temani karena ia kenal baik dengan paman.”
“Bagaimana kita bisa mencegahnya datang?”
“Dia manusia kejam. Di suratnya ia mengatakan akan menjemputku.”
“Biarkan dia datang. Tapi dia tidak akan bisa memaksakan kehendaknya,” tegas Willem, kembali masuk ke kamarnya.
Emosi Cornelia sedikit berkurang. Dari dapur Rabiyah membawa nampan berisi jagung rebus yang masih mengepul dan sebuah muk besar.
“Ini serbat, Non. Orang Jawa bilang wedang. Ada kayu manisnya,” kata Rabiyah, menuangkan isi muk ke dalam gelas dan meletakkannya di atas meja di samping Cornelia.
Dari depan terdengar suara pintu diketuk.
Tak lama ia kembali membawa sesuatu yang cukup berat. Harum buah durian menyergap ruangan.
“Ada titipan lima buah duren Suranadi besar-besar.”
“Untuk siapa?”
“Untuk Non Lia.”
“Dari siapa. Apa saya mengenalnya?” tanya Cornelia heran.
“Tidak. Non Lia bahkan tidak pernah bertemu. Namanya Babah Hongli. Dia punya toko bakpao.”
“Kalau tidak kenal kenapa mengirimkan saya durian? Kembalikan, inaq.”
“Tidak bisa, Non. Dia tadi bilang memberikan buah ini dengan ikhlas. Dia buru-buru pergi.”
“Jangan-jangan ada senggegernya itu, Inaq,” kata Cornelia. Ia telah banyak tahu tentang pelet orang-orang Sasak seperti yang sering diceritakan Rabiyah.
“Bukan, Non. Orang Cina saya tak pernah dengar pakai senggeger.”
“Orang Cina?”
Tiba-tiba Rabiyah tertawa terpingkal-pingkal. “Non, ini baru lima buah duren dari si babah. Non Lia sudah diketahui di seluruh Ampenan ini. Orang-orang semua tahu ada bidadari di rumah ini. Nah, besok, lusa, dan seterusnya, bukan cuma Babah Hongli menitip buah tangan. Bisa satu dokar manggis, salak, rambutan, bahkan ikan dikirim kemari untuk Non. Dari babah atau tauke lain. Juga abah, ncek-ncek, daeng, lalu, mamiq, pokoknya banyak.”
“Urus saja sendiri. Ambil sudah semua untuk Inaq, siapa tahu dapat jodoh lagi,” gerutu Cornelia, “Tiyang ngantok, tiyang mele tindok (saya ngantuk, saya mau tidur).”
Mendengar itu Rabiyah bertambah geli. “Wel te rusten, Prinses!” katanya mengucap salam. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)