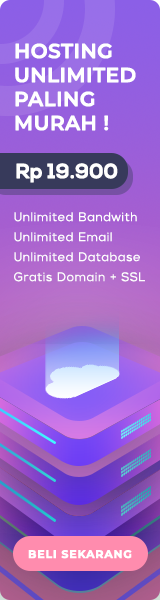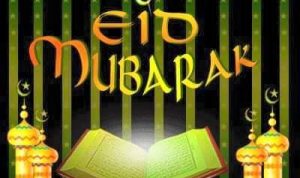BERBAGI News – Para buruh di Pelabuhan Ampenan sering menemukan surat kabar milik penumpang yang tertinggal di kapal. Salah satunya De Indische Courant, koran berbahasa Belanda yang terbit di Pulau Jawa. Di surat kabar inilah Multatuli (Eduard Douwes Dekker) menulis berbagai kritik tentang sistem pemerintahan kolonial Belanda.
Di tahun 1922, De Indische Courant memuat tulisan salah seorang pembaca yang bercerita tentang kisah perjalanannya ke Pulau Lombok. Dari Surabaya, tulisnya, Lombok dapat dicapai dengan salah satu kapal dalam dua puluh tujuh jam. Ongkos setiap penumpang 50 gulden. Sampai di Pelabuhan Ampenan para penumpang berdebat dan saling tawar dengan pemilik gerobak atau dokar. “Biaya sampai ke hotel atau pesanggerahan di Mataram sebesar 50 sen,” tuturnya.
Di pusat kota, di tengah Kebon Raja, taman yang tertata rapi, ada tulisan di prasasti sebuah tugu peringatan yang berbunyi: Eere den gevallenen in den strijd op Lombok 1894 (hormatilah yang gugur dalam pertempuran di Lombok 1894).
Kalimat yang seolah-olah mengandung pesan kepada pribumi. Bahwa apa pun perubahan dan kemajuan di Lombok, tidak terlepas dari peristiwa invasi Belanda di tahun 1894. Belanda yang telah menumpas kekuasaan Karangasem di Lombok, dengan pengorbanan perwira-perwira terbaiknya.
*
Jam tujuh pagi Cornelia dan Rabiyah sudah berada di Pelabuhan Ampenan. Gadis Belanda itu penasaran dengan cerita Rabiyah tentang penganan berbahan tepung beras yang dipanggang dalam sebuah cetakan dari tanah liat.
“Namanya serabi. Setelah matang ditaburi parutan kelapa dan gula merah yang sudah diencerkan. Adik perempuan saya menjualnya di sekitar pelabuhan,” kata Rabiyah.
Sepagi itu pelabuhan sudah ramai. Para lelaki sebagian besar telanjang dada. Ada yang mengangkat barang dari dokar, membawanya ke kapal yang bersandar. Seseorang mondar-mandir di dermaga, sebentar-sebentar memandang ke arah laut lepas.
“Belum ada nampak kapalnya,” katanya pada seseorang yang duduk membelakangi pantai.
“Kalau sampai siang nanti kapal belum juga masuk, sore kita cari rumput lagi. Sudah dua hari sapi-sapi itu kita berikan pakan untuk persediaan di kapal.”
Keduanya adalah pembantu kleder yang akan membawa sapi ke luar negeri. Sapi-sapi telah siap diberangkatkan, tapi kapal yang ditunggu belum tiba.
“Tumben telat.”
Noni dan perempuan pribumi itu duduk berjongkok di depan seorang wanita yang sedang membuat kue serabi. Para lelaki yang sedang minum kopi di sebuah kedai tak jauh dari tempat itu, sejak tadi memperhatikan sang noni. Obrolan yang tadinya terdengar riuh di warung itu tiba-tiba terhenti. Semua memandang tak berkedip. Di warung sebelahnya, seorang perempuan muda mencubit lengan lelaki di sampingnya. Ia nampak kesal. Ia mencubit lagi dengan keras. Tetapi lelaki itu seolah tak merasakannya. “Ndot-ndot ime kamu (diam-diam tanganmu)!” ia menegur tanpa menoleh. Matanya tetap tak berpindah dari sosok gadis molek beberapa depa di depannya.
Perempuan di sebelahnya kini benar-benar marah. Barangkali keduanya pasangan suami-istri. Tangannya meraih daun telinga lelaki itu, menarik dan memelintirnya keras sambil melangkah. Terdengar suara kesakitan. Lelaki itu seperti kambing yang diseret. Mereka meninggalkan tempat itu.
“Ndeq bau engat aik meneng (tak bisa melihat air jernih),” perempuan itu mengomel sepanjang jalan. Tangannya belum juga melepas daun telinga lelaki itu.
Seorang anak perempuan enam tahunan datang dari arah pantai. Tubuhnya dekil, tak berbaju. Ia duduk di samping penjual serabi.
“Raodah!” panggil Rabiyah. Ia bangkit mendekati anak itu. “Ini keponakan saya, Non Lia.”
Cornelia berdiri, tersenyum ramah. Ia mengusap kepala anak perempuan yang sedang dipeluk Rabiyah. Tapi anak itu nampak ketakutan. Ia mempererat pelukannya, membenamkan wajahnya di dada Rabiyah.
“Kenapa takut, ayo ikut ke rumah,” kata Cornelia dengan nada bersahabat.
Tapi tiba-tiba Raodah memberontak, melepaskan diri dari dekapan Rabiyah. Ia berlari sekencang-kencangnya, kembali ke pantai.
Kedua wanita itu melangkah pulang. Beberapa kusir dokar menawarkan tumpangan.
“Kita pulang naik dokar? Non Lia mungkin lelah,” kata Rabiyah.
“Tidak usah. Saya masih kuat jalan kaki.”
Di Jalan Pabean ada toko-toko yang menjual bermacam makanan. Di antaranya roti kering dari bahan beras. Makanan ini keras seperti batu. Tidak bisa langsung dimakan, tapi direndam dulu di dalam segelas air, teh, atau susu, sampai lunak. Roti yang bisa disimpan lama.
Di sepanjang jalan Rabiyah bercerita tentang gadis-gadis pribumi yang mempertahankan keperawanannya sebagai lambang kesucian. Kegadisan yang hanya diserahkan pada malam pertama, pada lelaki yang menikahinya.
“Inaq masih perawan saat malam pertama?”
“Tentu saja, Non. Saya menikah di usia 14 tahun. Suami pertama saya orang Arab.”
“Bagaimana malam pernikahan itu. Inaq bahagia?”
“Marak tesusuk sik anak alung. Ketinjot kembelas tiyang. Tiyang nyurak, Non (seperti ditusuk alat tumbuk. Saya terkejut. Saya menjerit, Non).”
Karuan saja, Cornelia tak dapat menahan tawa. Ia terpingkal-pingkal sambil memegang perut. Orang-orang melongo terpesona. Tawa renyah bidadari Eropa menambah segarnya pagi, di jantung Ampenan. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)