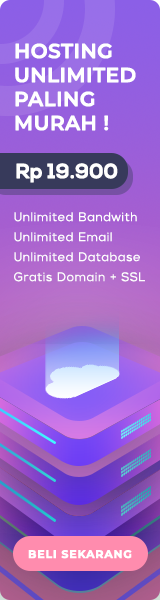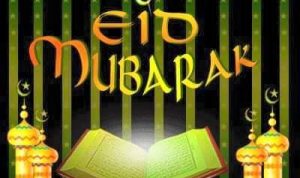“Dia baru beberapa bulan di sini,” kata Rabiyah sepulang dari pasar.
“Pemuda kemarin itu?” tanya Cornelia.
“Iya, Non. Orang-orang di pasar ramai membicarakan kejadian kemarin. Oya, Non, Raodah tak bisa datang. Sepulang dari pantai kemarin ia demam.”
“Kasihan. Dia pasti kaget. Kita jenguk dia habis Inaq selesai memasak.”
Rabiyah memasak tumis kangkung dan oseng-oseng tempe. Noni itu kini mulai familiar dengan masakan Nusantara. Sambil memasak Rabiyah melanjutkan cerita yang didengarnya tadi di pasar.
“Ia agak aneh. Jarang bicara. Ia tak pernah lama-lama berada di suatu tempat. Tempo hari ia membawa banyak kitab ke salah satu masjid. Ia serahkan kepada marbot, berpesan agar kitab dari ulama-ulama terkenal itu dibaca jamaah.”
Orang-orang tak tahu di mana pemuda itu tinggal. Tetapi ia sering berada di Kampung Melayu dan Karang Panas. Ia menyukai anak-anak.
Ada beberapa kejadian misterius yang berkait dengan sosok sang pemuda.
Di tengah hari yang panas, ia mengajak anak-anak yang berada di pantai minum es cendol jualan Jemuhur. Satu gelas satu anak. Belasan anak menikmati minuman dengan rakus. Ada banyak yang minta tambah lagi. Pemuda itu tertawa-tawa senang melihat anak-anak kecil itu berebutan mengambil gelas cendol di tangan Jemuhur yang tak henti-hentinya menyendok bahan minuman dari toples. Dalam waktu singkat cendol jualan itu habis. Benar-benar habis tak bersisa.
Tetapi pemuda itu pergi begitu saja, diiringi anak-anak kecil yang kekenyangan cendol sampai bersendawa. Jemuhur terpana. Dagangannya habis, tapi ia tak menerima sesen pun uang pembayaran. Ia kebingungan. Entah mimpi apa ia semalam. Kesialan menimpanya hari itu. Seumur-umur tak pernah dialaminya. Ia ingat ucapan istrinya sebelum berangkat berjualan pagi tadi. Beras sudah habis. Ia bertambah bingung. Ia merasa menjadi orang paling merana. Kepalanya mendadak pening. Di kejauhan ia masih melihat pemuda itu dikerumuni anak-anak di tepi pantai. Ia ingin menyusulnya, tetapi entah mengapa kakinya enggan melangkah. Di bawah pohon waru itu ia termenung.
Sebelum dhuhur ia mendorong rombong dengan lesu, pulang ke gubuknya di Dayen Peken. Istrinya sedang berdiri di depan pintu.
“Tumben cepat pulang.”
Jemuhur tak menjawab. Ia masuk ke gubuk berdinding gedek yang beratap rendah itu. Di atas lasah (balai-balai) ia merebahkan tubuhnya. Ia merasakan penat yang luar biasa yang membuat tubuhnya lemas. Pikirannya kacau-balau. Ia tak bisa memejamkan mata.
Dari luar terdengar teriakan istrinya memanggil namanya. Tapi ia tak kuasa bangkit. Tak lama perempuan itu masuk, membawa kotak dari kayu. Tempat Jemuhur menaruh uang hasil berjualan.
“Banyak sekali kau dapat jualan hari ini, Jemuhur. Banyak. Uang yang banyak sekali!”
Jemuhur merasa seperti tersengat kalajengking. Ia melompat dari balai-balai.
“Uang?”
Perempuan itu meletakkan kotak itu di balai-balai. Bola mata Jemuhur terbelalak. Kotak kayu itu hampir penuh dengan keping-keping uang Belanda. Berjualan tiap hari selama setahun pun ia tak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu.
Ia menceritakan kejadian di pelabuhan. “Sejak pagi belum ada seorang pembeli pun. Kotak itu kosong sejak dari rumah. Lalu dia datang bersama anak-anak kecil.”
Istri Jemuhur menyimak sampai suaminya selesai bercerita. “Lalu kita apakan uang ini?”
“Kamu beli beras beberapa liter. Lalu simpan baik-baik uang itu. Saya sekarang akan kembali ke pelabuhan mencari pemuda itu. Jelas-jelas hanya dia dan anak-anak itu saja yang berada di dekat saya. Sudah saya katakan tak ada satu pun pembeli sebelum mereka datang. Tapi saya tak memperhatikan kapan ia memasukkan uang itu ke dalam kotak. Apa maksudnya saya tak tahu. Kalau nanti ia ternyata keliru, kita kembalikan. Kita ambil mana yang menjadi hak kita saja.”
Jemuhur kembali ke pelabuhan. Tapi di pantai itu ia hanya melihat anak-anak yang tadi meminum jualannya. Ia bertanya ke mana pemuda itu. Tapi satu pun anak-anak itu tak ada yang bisa menjelaskan ke mana pemuda itu pergi. Jemuhur menyusuri lorong-lorong di Kampung Melayu. Bertanya kepada siapa saja yang dijumpainya di jalan. Lelaki itu mencari lagi ke kampung lain. Ke Gatep, Karang Panas, Sintung, Kampung Banjar, Sukaraja, hampir semua kampung di Ampenan dimasukinnya. Pemuda itu entah berada di mana. Sampai matahari hampir tergelincir di ufuk barat, Jemuhur tak berhasil menemukan pemuda itu.
Esoknya ia berusaha mencarinya lagi. Esoknya lagi. Demikian sampai hampir dua minggu. Pemuda itu seperti ditelan bumi.
Setelah ia matang dengan sebuah rencana, Jemuhur meminta kotak uang itu pada istrinya. Sebagian uang ia gunakan untuk menyewa tempat di pinggir jalan Otak Desa. Ia buka warung makanan. Sebagian lagi untuk membeli dokar lengkap dengan kuda yang tangguh. Ia percayakan kepada seseorang dengan perjanjian bagi hasil. Sejak itu hidupnya berubah makmur. Tetapi ia tetap berusaha mencari pemuda itu. Kepada orang-orang yang datang ke kedainya, ia berpesan jika bertemu dengan pemuda itu, agar menyampaikan salam hormatnya, dan memintanya berkunjung ke tempatnya.
Cornelia hanyut mendengar penuturan Rabiyah. Cerita yang mengesankan.
“Ada lagi kisah mengenai pemuda itu, saat menolong tiga orang yang terlantar di Lombok. Mereka dari Sumatera,” lanjut Rabiyah.
Ketiganya ingin kembali pulang ke kampung halaman. Mereka bertemu pemuda itu di emper toko Sinar Biru di Jalan Pabean.
“Ikuti saya,” kata pemuda itu.
Mereka berjalan ke pelabuhan. Pemuda itu terus melangkah ke dermaga. Ada kapal yang sebentar lagi berangkat pagi itu. Ketiga perantau itu berhenti, saling bertatapan. Mereka ragu. Tapi pemuda itu berkata lagi, “Ikuti saya.”
Beberapa petugas berseragam berjaga-jaga di dermaga dan pintu masuk kapal. Tetapi mereka tak bertanya apa pun kepada sang pemuda, juga ketiganya. Pemuda itu mengantar ketiganya sampai di atas kapal. Begitu ia turun, kapal melepas jangkar. Kapal perlahan meninggalkan dermaga. Tiga orang itu melambaikan tangan, tetapi pemuda itu tak melihatnya. Ia meninggalkan pelabuhan. Kapal semakin jauh.
“Siapa namanya?” tanya Cornelia.
Sebelum Rabiyah sempat menjawab, Willem muncul di ruang tengah. “Ada surat untukmu, dari paman,” katanya, memberikan sepucuk surat dalam sampul coklat.
Satu jam kemudian Cornelia dan Rabiyah berada di Kampung Melayu Bangsal, di sebuah pondok beratap rumbia berlantai tanah. Di situlah Raodah tinggal.
Ibunya duduk di sampingnya berbaring di atas balai-balai dari bambu yang sudah berlubang-lubang digerogoti rayap.
Begitu melihat kakak perempuannya dan gadis Belanda itu datang, ia buru-buru ke luar, meminjam tikar pandan milik tetangganya.
Cornelia meraba kening gadis kecil itu. Ia ambil handuk kecil di dalam bungkusan, dan meminta Rabiyah mengambil air. Ia mengompres dahi Raodah.
Gadis kecil itu terbangun. Menyadari kehadiran Cornelia, ia memaksa sebuah senyum.
“Cepat sembuh, adikku. Kakak sudah siapkan sebuah lagu bagus untukmu. Kamu harus bisa nyanyikan. Kamu pasti suka,” kata noni itu perlahan. Ia mencium pipi Raodah.
Gadis cantik itu menoleh kepada ibu Raodah yang duduk di bawah di atas tikar, “Bibi, kalau Raodah tidak ada nafsu makan, buatkan ia susu dan ada roti tawar dan mentega di dalam bungkusan. Besok pagi kalau panasnya belum turun, bawa ke rumah. Biar diperiksa Dokter Willem.”
Cornelia bertanya di mana ayah Raodah. Dua bersaudara itu saling berpandangan.
“Maaf, Non, saya belum cerita. Sudah tiga tahun ayah Raodah menghilang. Ia bersama lima nelayan melaut pada suatu malam. Perahu itu tak pernah kembali. Kami sudah pastikan mereka tenggelam di laut lepas,” jelas Rabiyah.
Wajah Cornelia nampak berduka.
Di luar tiba-tiba ramai. Orang-orang datang berbondong-bondong. Bergiliran memandang ke dalam dari depan pintu.
Mereka bukan datang menengok anak yang sakit, tapi ingin melihat rembulan Eropa yang santer menjadi buah bibir di seantero Ampenan.
“E neneq kaji sak kuase. Anak sai dedare ne. Lamun bedoe anak sak aran malaikat, ye paut jari anak malaikat (Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak siapa gerangan gadis ini. Jika yang bernama malaikat itu punya anak, dia pantas jadi anak malaikat),” terdengar ucapan dari seorang perempuan lima puluhan. Ia duduk paling depan. Tubuhnya kurus kering. Sebentar-sebentar ia menyedot rokok kelobot yang terjepit di jarinya. Asap mengepul masuk ruang depan gubuk yang sempit itu.
“Sai aran noni tie?” menimpal suara perempuan lain.
“Cornelia,” jawab seorang pemuda bertelanjang dada.
“Ke solah aran’n (bagus/indah sekali namanya).”
“Ye mule solah. Selapuk’n solah. Ndek marak kamu. Selemok aran’m. Dedare toaq bideng leteng (memang indah. Semuanya indah. Tidak seperti kamu. Namamu Selemok. Gadis tua hitam pekat),” menjawab lagi pemuda tak berbaju. Lalu terdengar tawa riuh rendah.
“Ngkah uyut, arak kanak sakit (berhenti ribut, ada anak sakit),” perempuan bernama Selemok membentak.
Tapi ia tertawa juga. Memperlihatkan giginya yang besar-besar dan hitam bekas kunyahan sirih yang sulit hilang. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)