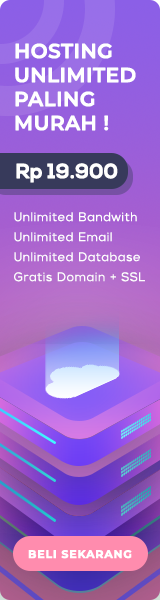BERBAGI News – Beberapa ratus meter di utara jembatan Meninting, ada kebun nyiur yang cukup luas. Pemiliknya seorang warga Tionghoa di Ampenan.
Siang itu, Jero Alit, penunggu kebun, bersama istrinya, sedang sibuk memanggang belasan ikan kakap merah sebesar betis dan beberapa ekor ayam.
Dua kendaraan berhenti di jalan. Enam pasang muda-mudi Belanda turun, memasuki kebun nyiur. Angin berhembus dari arah pantai, membawa aroma asin laut. Mereka duduk membentuk lingkaran di atas hamparan rumput hijau segar seperti permadani di antara batang-batang kelapa yang tinggi menjulang. Para sinyo dan noni itu duduk berpasang-pasangan.
Seorang pemuda membuka sebuah botol minuman keras, menuangnya ke dalam gelas-gelas. Minuman itu diedarkan, masing-masing segelas.
“Untuk Letnan Graaf Maarten, serdadu gagah perkasa Hindia Belanda yang baru tiba dari Batavia. Dan untuk Nona Cornelia Doutzen, pianis termasyhur dan gadis terindah di Rotterdam. Mari bersulang,” kata Joan van Dirk.
Kedua belas pemuda-pemudi itu bangkit, mengangkat gelas masing-masing. Gelas-gelas berdenting. Mereka menghabiskan isinya sekali teguk. Hanya gelas Cornelia yang isinya masih utuh. Ia tak pernah menenggak minuman beralkohol.
Semua menatap pasangan yang berdiri di tengah-tengah lingkaran itu. Lima gadis tak dapat menyembunyikan perasaan iri. Kecantikan mereka tak ada apa-apanya dibanding pesona dan pancaran keanggunan sosok dara Rotterdam itu. Dipandang seperti itu Cornelia menjadi kikuk.
Mereka duduk kembali. Gelas-gelas yang kosong kembali diisi. Botol dibuka lagi. Hidangan ayam dan ikan bakar yang masih mengepul diantar Jero Alit dan istrinya ke tengah-tengah mereka.
Joan terus bercerita tentang kehebatan Graaf di serangkaian pertempuran di Pulau Jawa dan Sumatera. “Pemuda yang sangat pemberani. Tak ada urat takutnya. Pada iblis pun ia tak gentar. Bahkan atasannya seorang peranakan pribumi-Belanda ia pernah tonjok hidungnya sampai patah. Ia pernah dikeroyok tiga inlander bersenjata tajam setelah habis minum di kawasan Menteng. Ia berhasil merebut pisau salah seorang penyerang. Dengan senjata itu ia mengamuk. Seorang tertikam biji matanya. Seorang lagi ia potong salah satu telinganya.”
Penuturan Joan diselingi decak kagum orang-orang yang mulai mabuk.
Keberanian pemuda tampan ini, lanjut Joan, membuat para gadis di Batavia tergila-gila. “Mereka memperebutkan sang pahlawan Hindia Belanda,” ucapnya sambil menatap Cornelia, berharap wanita itu menunjukkan sikap cemburu. Tetapi gadis itu tak bereaksi apa pun.
Graaf duduk tegak membusungkan dada. Ia mengangkat gelasnya lagi, meminta minuman dituangkan.
Matahari telah jauh melewati batas siang. Tiga jam telah berlalu. Tetapi belum ada tanda-tanda mereka bersiap pulang. Botol-botol minuman yang telah kosong bergeletakan, tetapi ada beberapa yang belum dibuka. Graaf menuang lagi minumannya.
Beberapa gadis duduk di pangkuan pasangan masing-masing. Ada yang bertindihan di rerumputan. Berguling-guling tanpa melepas pelukan. Mereka tak peduli lagi pasangan lainnya. Tiga gadis dalam keadaan setengah telanjang.
Graaf menggeser duduknya merapat ke samping Cornelia. Tangannya ia letakkan di pundak gadis itu.
Tapi Cornelia segera bangkit. “Antar saya pulang. Saya sebenarnya tidak mau ikut tadi, asal kau tahu.”
“Pulang? Pulang ke mana? Ini tempat kita. Kita menginap di sini,” Graaf ikut bangkit. Tangan kirinya memegang gelas, sebelahnya lagi mencoba merangkul Cornelia.
Gadis itu melangkah mundur. Graaf meneguk minumannya, melempar gelas yang telah kosong. Ia bergerak maju memburu Cornelia.
Cornelia berlari. Tapi sekali melompat, Graaf mendapatkan mangsanya. Ia bungkam mulut gadis itu. Dengan buas tangannya memeluk. Tapi gadis itu tak terima. Ia menjerit dan meronta-ronta. Lengan yang memeluknya ia gigit sekuat-kuatnya. Tetapi ia seperti menggigit kulit yang sangat alot. Serdadu keji itu tak merasakannya. Sifat aslinya kini benar-benar ditunjukkannya. Sekali renggut, dua buah kancing atas baju Cornelia terlepas. Cahaya sore menerpa dada gadis itu yang setengah terbuka. Ia sandarkan tubuh Cornelia di pokok kelapa. Tubuh besar Graaf menghimpit. Tangannya menggerayangi tubuh putih mulus dan padat berisi itu.
Cornelia terus menjerit. Suaranya yang melengking tidak membuat seorang pun di tempat itu bergerak menolongnya. Pasangan-pasangan itu tak terusik, terseret ke pusaran arus birahi yang menenggelamkan jiwa dan raga.
Cornelia putus asa. Ia merasa berada dalam cengkeraman raksasa yang siap menelannya. Tetapi telinganya mendengar sebuah ucapan.
“Assalamu’alaikum.”
Suara itu bergema di seluruh area kebun kelapa di pesisir pantai itu. Terasa tanah yang dipijaknya bergetar. Juga batang pohon tempatnya bersandar.
Cornelia menoleh. Sepuluh langkah di arah utara ia melihat sesosok tubuh melangkah mendekat. Ia segera mengenalinya. Pemuda yang pernah menolongnya dari amukan sapi gila, dan penyelamat Raodah ketika digulung gelombang pasang.
“Wa’alaikumsalam,” Cornelia menjawab salam. Ia setiap hari mendengar salam yang diucapkan mayoritas muslim di kampung-kampung di Ampenan.
Pemuda tampan itu semakin mendekat. Graaf juga melihatnya. Tapi ia tak bergerak dari tempatnya berdiri. Begitu ia mendengar salam itu, tangannya melepaskan tubuh gadis itu.
Senyum pemuda itu mengembang. Ia ulurkan tangannya. Cornelia menyambutnya. Ia selipkan jemarinya di antara jari-jari tangan sang pemuda.
“Ikut saya,” kata pemuda itu.
Dua manusia berbeda bangsa ini meninggalkan Graaf yang berdiri gontai. Ia menatap keduanya seperti orang yang sangat dungu. Dari belakang terdengar seruan. “Kenapa kau tak tembak batok kepala bangsat inlander itu?”
Graaf menoleh, tapi tak menjawab. Ia tetap berdiri di tempat itu.
Sayup dan sayup, aroma yang beberapa kali pernah terhirup, kini datang lagi. Dan kali ini ia berada di taman yang lebih indah, lebih luas, tak berbatas. Ia kini tak sendiri. Ia bersama lelaki yang sering muncul di mimpi-mimpinya. Jika dalam mimpi-mimpi itu ia tak pernah berhasil menyentuhnya, kini ia sedang berjalan sambil bergandengan tangan. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin dipeluk, dibelai, dicium. Tetapi, sedangkan dalam genggaman jemari pemuda itu saja, ia merasakan sensasi luar biasa, perasaan romantis yang tak terhingga yang sulit diurai kata-kata. Seluruh pembuluh darahnya seperti disusupi melodi terindah, susunan nada-nada yang rasanya tak mampu ia lampiaskan di tust-tuts piano. Taman indah. Nada indah. Aroma indah. Melebihi keharuman bunga-bunga di Rotterdam, Den Haag, atau di mana pun di seluruh sudut negerinya. Aroma yang sensasinya bahkan tak mampu dicapai parfum-parfum yang sering dibelikan ayahnya di Paris. Mereka terus berjalan. Taman tak berbatas. Tapi bersama sang pemuda ia tak merasa lelah sedikit pun. Suasana seolah menghentikan waktu, sehingga matahari hanya menyorotkan sinar senja yang selalu menciptakan hati yang rawan. Waktu terindah. Waktu-waktu merindu.
Gadis Rotterdam itu seperti terbangun dari mimpi, ketika pemuda itu melepaskan tangannya.
“Sampai di sini saya mengantarmu,” katanya.
Di hadapan mereka sebuah dokar menanti. Pemuda itu mempersilakannya naik.
Cornelia cemberut ketika pemuda itu tak ikut bersamanya di atas dokar. Wajahnya nampak merajuk.
“Mengapa kamu tidak mengantarku sampai ke rumah?”
Pemuda itu tersenyum. Senyum seribu wibawa. Senyum yang membuat Cornelia ingin melompat dari dokar, mengejarnya dan tak ingin pulang.
“Kusir Acip menemanimu sampai rumah,” jawabnya.
Dokar berjalan. Hentakan tapak kuda menerbangkan debu jalanan. Petang merayap, meremang. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)