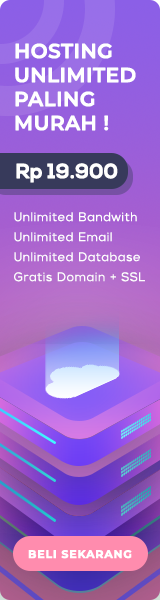BERBAGI News – Di Batavia Cornelia merasa tak betah. Walaupun di kota ini banyak tempat pelesiran, siang dan malam, ia sama sekali tak pernah bisa menikmatinya. Di rumah pamannya, ia sebenarnya tak pernah kesepian. Tamu-tamu datang silih berganti. Teman-temannya cukup banyak. Ada banyak anekdot dan pengalaman konyol yang diceritakan kawan-kawannya. Semuanya lucu, tapi tak bisa menghiburnya. Ia ikut tertawa mendengarkan, tetapi tertawa yang dipaksa-paksa.
Batavia yang metropolis, tak mampu mengalihkan ingatannya pada kota kecil yang tak nampak dalam peta bumi. Ampenan. Nama itu kini begitu indah, bahkan melebihi kota kelahirannya, Rotterdam, kota bandar termasyhur di dunia.
Betapa Ampenan telah mengikat hatinya. Walaupun kota kecil itu belum semua ia susuri. Dan belum terlalu banyak orang-orang di sana yang ia kenal dan akrabi. Inilah yang sulit ia pahami. Sebuah daerah yang lebih banyak kaum miskinnya. Belum dikatakan modern. Sarana prasana yang masih terbelakang. Rumah-rumah yang kusam. Jalan-jalan berdebu. Kuda-kuda penarik dokar berak di jalan. Anjing, kucing, bebek, ayam, berkeliaran seperti tak bertuan. Anak-anak yang tak berbaju, bahkan telanjang bulat. Apa yang membanggakan di kota itu?
Tapi gelombang itu. Gelombang laut yang selalu lapar, melibas, menenggelamkan. Menggulung menciptakan ombak. Suara deburnya memanggil-manggil namanya.
Kembali ia teringat Rabiyah. Perempuan itu benar-benar inaq-nya. Inaq yang sering mengeramasi, menyisir, mengepang rambutnya. Inaq yang memijat tubuhnya, menyelisik kulit kepalanya, ketika ia sulit memejamkan mata. Dan ia tertidur pulas setelah itu. Muncul pula senyum Raodah yang menggemaskan, gadis kecil itu. Matanya besar, hidungnya tak pesek seperti pribumi kebanyakan. Bibirnya mungil. Kulit sawo matang. Tiga atau empat tahun lagi ia akan menjelma menjadi gadis jelita, berwajah mirip perempuan-perempuan Latin.
Dan, ah… Pemuda itu. Tubuhnya tak sebesar lelaki-lelaki Eropa. Tetapi, ia jauh lebih gagah, lebih tampan, senyumnya selalu membuat debaran di jantungnya. Tubuh dan wajahnya memancarkan seribu wibawa. Ia tak pernah tahu namanya sampai saat ini. Tapi mengapa hampir setiap waktu ia seakan berada di dekatnya? Mengapa ia tak pernah berhenti memikirkannya?
Ia dekatkan telapak tangannya, juga pergelangan tangannya, ke depan wajahnya. Ia pejamkan mata. Sayup. Sayup aroma itu masih membekas. Tak hilang-hilang. Jemari lelaki itu pernah menggenggam tangannya. Dan ia merasakan kaki tak berpijak, melayang, terbang. Ia mencoba keluar dari dalam dirinya, memandang dengan akal sehat. Barangkali pemuda itu tak pernah tertarik padanya. Tak seperti lelaki-lelaki yang menatap terpesona setiap ia berjalan. Tak seperti lelaki-lelaki, tua dan muda, yang bermain gasing di ujung jembatan Ampenan. Baik ncek, daeng, tauke, abah, babah, tuaq, amaq, mamiq, atau dae yang ingin mendapat perhatiannya. Tetapi, mengapa ia selalu datang menyelamatkannya, di saat yang kritis, di saat-saat orang lain tak mungkin bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukannya? Pasti, pasti ia sangat cemburu, ketika Graaf membawanya pergi bersama teman-temannya ke kebun nyiur itu. Bagaimana ia tiba-tiba ada di saat yang tepat, ketika Graaf mencoba memperkosanya, ketika ia benar-benar butuh pertolongan? Pemuda itu pasti mengamati-amati dari kejauhan sejak ia pergi. “Ia jelas menyukaiku, selalu memperhatikanku tanpa setahuku,” Cornelia membathin, menyenangkan-nyenangkan dirinya. Tapi ia kembali bimbang.
Ia selalu gelisah setelah meninggalkan Lombok. Dua minggu setelah berada di Batavia, ia menulis surat kepada Willem, mengabari tanggal kepulangannya.
Tiga hari berturut-turut sebelum keberangkatannya, ia keluar-masuk kampung-kampung di Batavia. Ia melihat pola kehidupan jelata Betawi yang tak jauh beda dengan penduduk Sasak. Ketika mendengar mereka bicara, ada banyak kata yang sama, pengertiannya juga sama. Misalnya demen, awak (badan), porot, gedeg (sebal), kedebong, ngesot, pelesir, bejeg, grusuk, uber, dan beberapa partikel, antara lain doang dan dong. Bedanya, kalau orang Betawi mengatakan “ayo dong”, di Lombok menyebut “dong ayo”. Seperti orang-orang Betawi pula, orang-orang di Ampenan juga ber-ana ente.
*
Di ujung dermaga puluhan orang menanti kedatangannya. Dari anak-anak, muda-mudi, sampai mereka yang sudah bangkotan. Mereka yang hampir uzur ini berpenampilan paling rapi dan paling wangi. Bahkan ada yang berpantalon dan menggunakan jas lengkap dengan dasinya. Tiga di antara mereka adalah Daeng Salam, Abah Karim, dan Ncek Hanafi.
“Kapalnya sudah bersandar,” kata seseorang.
Ucapan itu seperti aba-aba. Dua puluhan lelaki melompat ke jembatan, seperti berlari menuju kapal.
Gadis itu masih berada di bangku penumpang. Orang-orang masih antri ke luar kapal.
“Noni!”
“Cornelia!”
Segerombol orang memasuki ruangan. Terdengar hiruk-pikuk karena banyak yang berteriak memanggilnya. Cornelia tersenyum gembira, melihat orang-orang berbondong-bondong menjemputnya.
“Inaq! Raodah!” ia ikut berteriak.
Perempuan-perempuan yang ikut menjemput memeluk dan menyalaminya.
“Tambah seperti bidadari pulang dari Batavia,” kata Daeng Salam sambil menyalami Cornelia. Ketika ia hendak mencium tangan gadis itu, ia didorong Abah Karim sampai ia hampir terpelanting. Saudagar kurma itu juga tak sabaran ingin bersalaman.
“Barang-barang Non Lia mana?” tanya Rabiyah.
Cornelia menunjuk bawaannya.
“Wah, banyak sekali barang-barang ini. Ayo, kita bawa ke luar,” kata Ncek Hanafi.
Abah Karim memikul bungkusan paling besar dan berat.
“Wah, itu harus diangkat dua-tiga orang,” kata Cornelia.
“Sttttt,” Rabiyah meletakkan telunjuk di depan bibirnya.
“Itu beratnya hampir setengah kuintal, Inaq. Kasihan bapak itu.”
“Biarkan saja. Abah itu kajuman.”
Seorang pemuda menyusul di belakang Abah Karim. Ia membawa kopor.
“Abah, kalau capek nanti ana gantikan ponggok (pikul).”
“Ana sebiaq cucuk ente nanti (saya cabein mulutmu nanti). Ente belum dengar cerita. Ana pernah baku hantam dengan preman Tanjung Perak. Bobotnya satu kuintal lebih. Besar tinggi. Ana piting lehernya. Tinju ana menghantam, sampai pecah empedunya. Terkapar dia. Ana angkat dia sebelah tangan. Ana buang ke laut. Terlempar dia tiga puluh meter lebih.”
Barang-barang sudah sampai daratan. Tiga dokar dibutuhkan untuk mengangkutnya.
“Rabiyah,” panggil Abah Karim.
“Iya, Abah.”
“Besok lusa ajak noni ke rumah. Ambil satu karung kurma di sana,” katanya setengah berteriak.
*
Rabiyah mendapat oleh-oleh tiga kain sarung, empat kain batik, tiga kebaya, dua daster, dan sebuah gaun putih gaya Eropa, dan dua pasang selop dan sepatu. Ia mencoba semuanya. Ketika ia mengenakan gaun itu, ia berputar-putar, menari-nari. Tiba-tiba ia mengangkat roknya tinggi-tinggi.
Cornelia terkejut. Ia lihat sesuatu di balik rok itu. “Sudah, sudah! Inaq belang (genit) sekali,” seru gadis itu cekikikan. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)