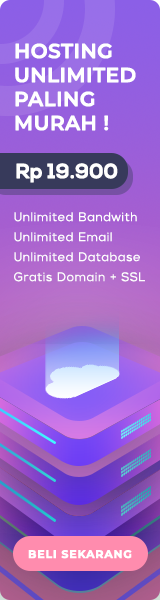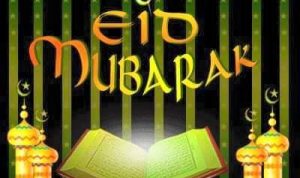BERBAGI News – Betapa takjubnya Raodah ketika mendengar alunan musik yang keluar dari benda mirip corong yang sering digunakan babah-babah penjual minyak tanah atau minyak kelapa di Ampenan. Tapi corong itu ukurannya lebih besar. Warnanya kuning keemasan, terbuat dari tembaga.
“Namanya gramophone. Musiknya berasal dari benda ini,” jelas Cornelia menunjukkan plat piringan hitam yang sedang berputar, “Benda seperti jarum ini namanya stylus, inilah yang meneruskan ke corong pengeras suara. Untuk menghidupkan gramophone, putar dulu alat di sampingnya.”
Perangkat itu dibeli Cornelia sejak ia masih di Rotterdam. Saat kedatangan pertama ke Lombok, banyak barang miliknya dititip di rumah pamannya di Batavia. Barang-barang yang kini ia bawa ke Ampenan, di antaranya koleksi ratusan piringan hitam dan beberapa alat musik.
Benda-benda itu ia tempatkan di ruang lantai atas. Ia kini banyak menghabiskan waktu di ruangan ini.
Raodah semakin banyak mendapat pengetahuan dari gadis Belanda itu. Kini, ia tak hanya diajari bernyanyi. Gadis kecil ini juga diperkenalkan beberapa alat musik.
“Ini biola, orang Inggris menyebutnya violin. Alat musik gesek,” kata Cornelia sambil memainkan lagu Angin Alus.
Mata bocah itu tak berkedip, menatap penuh minat. “Apakah kakak juga akan ajari saya memainkan alat itu?”
“Tentu saja. Kamu harus menguasainya.”
Cornelia juga memainkan gitar dan harmonika. Raodah tak henti-henti terpesona.
“Yang besar itu juga biola?”
“Bukan, itu bas cabik. Dimainkan sambil berdiri.”
Sejak itu rumah Dokter Willem sering dikunjungi anak-anak. Alat-alat musik itu menjadi buah bibir setelah Raodah bercerita pada teman-temannya.
Seorang anak lelaki seusianya hampir setiap hari datang. Namanya Utih. Ia anak Kampung Banjar. Ia diajari noni itu memainkan gitar.
Minat anak-anak itu sangat tinggi, untuk mempelajari memainkan peralatan musik yang baru mereka kenal. Dengan cepat beberapa di antaranya menguasai sejumlah lagu, mulai tembang lokal hingga lagu-lagu klasik yang kesohor di Eropa.
Di suatu sore Raodah dan Utih memainkan sebuah lagu di arena pegangsingan. Para lelaki yang sedang bermain gasing menghentikan keasyikan mereka. Pertama terkesima melihat benda aneh di tangan kedua anak yang memainkannya. Kedua, instrumentalia itu sungguh merasuk ke dalam hati. Mereka tertegun. Ada semangat yang terpendam selama berabad-abad terwakilkan dalam nada-nada yang mengalun.
“Itu diajari Noni Cornelia?” seseorang bertanya setelah lagu berakhir.
“Iya. Saya juga bisa menyanyikannya.”
“Coba.”
Dua anak itu berdiri. Tubuh mereka tegakkan, tangan lurus ke bawah. Kaki dirapatkan. Pandangan lurus ke depan.
Raodah memberi isyarat, menyebut angka-angka dari satu sampai empat. “Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, mulai!
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Semua mata memandang kedua anak yang sedang bernyanyi. Ketika sampai pada bagian “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”, mata mereka berkaca-kaca.
Lagu itu menghentikan aktifitas bermain gasing. Inaq-inaq penjual makanan pun ikut berdiri, menyimak sampai tuntas. Lagu yang membuat tubuh-tubuh mereka bergetar, bulu-bulu di sekujur tubuh terasa berdiri.
“Ulangi lagi.”
Raodah dan Utih mengulang lagi. Kali ini ada beberapa yang mengikuti mereka. Lagu diulang sampai belasan kali, sampai akhirnya hampir semua orang yang berada di tempat itu menghafalnya.
Cornelia muncul. Ia baru selesai mandi. Rambutnya masih basah. Ia seperti bunga mekar yang baru tersentuh cahaya matahari pertama. Gadis itu merasakan suasana yang berbeda, tak seperti hari-hari kemarin. Tak ada seorang pun memainkan gasing. Semua berdiri tegak, bernyanyi bersama, diiringi gesekan biola Raodah dan petikan gitar Utih. Tiba-tiba ia terharu. Ia tersenyum bahagia.
Menyadari kehadirannya, nyanyian bertambah keras. Tapi suara Daeng Salam paling dominan. Suaranya tak bagus, tapi sangat bersemangat. Puluhan pemain gasing dari sejumlah suku bangsa, Tionghoa, India, Arab, Melayu, Bali, Jawa, Sasak, Samawa, Mbojo, Padang, Aceh, Banjar, Bugis, Makassar, Bajo, Betawi, hanyut dalam sebuah nyanyian yang menggetarkan sanubari.
Senja itu, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya berkumandang di Ampenan. Di ujung jembatan. Di tepi Sungai Jangkok. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)