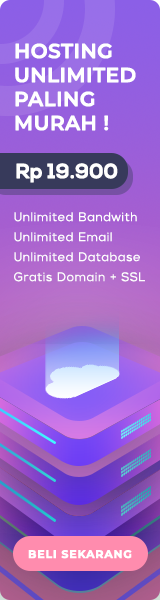BERBAGI News – Ahmad mengenakan pakaiannya. Di atas rumah panggung sudah tersedia hidangan untuknya. Dari mana pertapa itu mendapatkan makanan, ia tak terlalu peduli. Perutnya sangat lapar.
Ia ingat rumahnya. Entah sudah berapa lama ia menghilang. Orang-orang pasti mencarinya.
Ahmad mengeluh. Mengapa ia selalu membuat orang-orang susah memikirkannya. Mengapa ia tidak dilahirkan seperti anak-anak lainnya.
Orang-orang menganggapnya aneh, bahkan tak sedikit mengatakan ia sinting. Ia sering terlihat bercakap-cakap sendiri. Padahal ia sedang berkomunikasi dengan teman bicara yang tak terlihat mata awam. Ia sering menjawab dengan kata-kata yang tak dimengerti, lantaran di saat yang sama ia juga menjawab pertanyaan dari makhluk alam lain.
Ia ingin menjelaskan semuanya. Tetapi apakah orang-orang bisa mempercayai omongannya? Ia akhirnya memilih lebih banyak menyendiri, daripada mengundang pertanyaan yang pada akhirnya mencemooh dirinya, bahwa ia manusia ganjil.
Sampai akhirnya ayahnya bertemu seseorang di Lombok Tengah. Kepadanya ia dititipkan. Lelaki yang sudah dianggapnya orangtua ke dua. Seorang yang memahami sebuah dunia yang terbaca dalam sikap dan perilakunya. Ia sangat berarti, membangun kepercayaan dirinya. Bahwa sesuatu yang terlahir itu adalah kehendak Yang Maha Berkuasa atas kehidupan.
Sambil Ahmad menikmati makanannya, sang pertapa bercerita. Malam yang hening, suaranya terdengar jelas walaupun diucapkannya pelahan.
“Aku memilih jalur kebaikan, seperti yang terus dibisikkan di telingaku. Kebaikan yang lebih dekat dengan kebenaran. Tapi tak mudah mempelajari sesuatu yang baik. Aku mengembara ke banyak tempat. Satu manusia baik, hanya dapat diimbangi seribu jin pilihan. Fisikku manusia, tapi kemuliaan manusia tak mengalir dalam darahku. Dimensi yang tak pernah sanggup kuselami, walaupun telah lebih dari seribu tahun kupelajari. Aku tetap golongan jin.”
Ghalib berhenti sejenak. Ia menarik nafas panjang. Rumah panggung itu bergetar beberapa lama.
“Manusia saling bertikai, masing-masing merasa benar. Pada akhirnya kebenaran menjadi benih silang pendapat, sering berakhir dengan pertumpahan darah. Inilah yang semakin tak kupahami. Senjata-senjata diciptakan. Dengan dalih mempertahankan kebenaran, manusia memperkuat diri, dengan segala cara.”
Ahmad telah menghabiskan makanannya. Ghalib melanjutkan, “Lalu tersebar kabar tentang adanya suatu sumber energi teramat kuat yang berada di sebuah pulau. Sumber energi dari sebuah pohon. Di pulau ini, tepatnya di Gunung Rinjani. Sebuah pohon pertama sejak Pulau Lombok muncul dari dasar samudera.”
“Pohon besar? Bisa berkembang biak?” tanya Ahmad.
“Batangnya cukup besar dan berdaun lebat. Benihnya bisa tumbuh. Tapi butuh waktu satu juta tahun untuk bisa menghasilkan kualitas seperti pohon yang masih diburu sampai sekarang, di hutan Rinjani. Tak sembarang orang bisa melihatnya.”
“Kenapa pohon itu diburu?”
“Energi dalam inti zat di pohon itu sangat banyak manfaatnya, jika digunakan untuk tujuan yang baik. Manusia, hewan, dan makhluk tak kasat mata menyukai aromanya. Keharuman yang membuat tenteram. Banyak digunakan untuk terapi. Tetapi lebih banyak orang menyalahgunakannya. Zat yang mampu menyatukan kekuatan manusia, hewan, dan makhluk yang tak terlihat. Mereka para pemuja setan juga memburunya sebagai salah satu dari senyawa pembuatan ramuan untuk kehidupan abadi.”
Pertapa itu berdiri, memandang ke luar. Hewan-hewan malam beterbangan di bawah cahaya rembulan. Burung-burung hantu memperdengarkan suaranya yang seram. Unggas yang di Lombok disebut keas, kemunculannya dihubung-hubungkan dengan kehadiran selaq (leak) yang sedang bergentayangan. Sebentar-sebentar terdengar kepakan sayap kelelawar. Mulai dari yang kecil sampai yang bentangan sayapnya mencapai dua depa.
“Tugasmu melindungi pohon itu.”
“Mengapa harus saya, apakah saya sanggup, dan mengapa bukan Kakek sendiri yang memang pantas menjaganya?”
Ghalib menatap Ahmad lekat-lekat. Pandangan yang terasa menembus hingga bathin sang pemuda.
“Aku telah hidup lebih dari dua ribu tahun. “Aku tak pernah bilang tugas itu ringan. Aku pun mengalami sesuatu yang hampir sama denganmu.”
Ghalib menuturkan, ia dikucilkan sejak kecil. Bedanya dengan Ahmad, Ghalib dilahirkan dari sepasang jin. Fisiknya yang kasat mata, menyebabkan ia dijauhi kaumnya.
Dua puluh abad lebih ia telah berusaha membentengi pohon itu, namun ia selalu kewalahan. “Aku sudah katakan, aku bukan kalangan makhluk paling mulia. Dengan sesama jin pun, aku banyak mendapat tentangan. Hanya manusia yang mampu mempersatukan kekuatan seluruh hewan dan segala yang tak kasat mata. Kemampuan yang pernah dimiliki Nabi Sulaiman. Kemampuan membangun keharmonisan kehidupan di dunia, hanya dapat dilakukan orang yang tak punya kepentingan. Itu ada padamu, Ahmad,” ucapnya. “Aku sudah melihat kemampuan itu sejak kau baru dilahirkan. Enam belas tahun lalu, umurmu baru sehari saat itu. Kubawa kau ke puncak Rinjani. Kuteliti semua pembawaan yang kau bawa sejak lahir. Kau dianugerahi kecerdasan di atas orang-orang biasa. Di darahmu mengalir kewibawaan dan kemuliaan manusia yang membuat kau disegani alam dan segala makhluk.”
“Betapa beratnya tugas itu, Kek,” Ahmad mengeluh.
Ghalib mengeluarkan guci kecil dari balik jubahnya. “Seorang tabib di lembah Sungai Nil, sampai ke Lombok, beberapa abad sebelum aku dilahirkan. Ia dapatkan beberapa bongkah inti dari pohon itu. Ia murnikan menjadi senyawa inti yang dimasukkan ke dalam tiga guci kecil.”
Pertapa itu meneruskan, “Konon, tiga guci persembahan sang tabib, adalah salah satu andalan Minephtah putra Ramses II sehingga berani menuhankan dirinya. Dua guci sudah habis digunakan. Satu guci ini berhasil kuselamatkan.”
Malam berganti dinihari. Tapi Ghalib terus bicara. “Ahmad, berabad-abad aku mendalami berbagai kesaktian. Tetapi kau hanya butuh waktu tiga hari tiga malam untuk menguasai segala yang pernah kupelajari. Itu bukti kau bukan manusia biasa. Tiga tetes senyawa itu telah menyatu dengan dirimu. Kekuatan gaib bisa kau kendalikan dengan pikiranmu. Ada tiga ribu jin yang menyertai ke mana pun kau pergi, siap melaksanakan perintahmu. Dan saat kau dalam keadaan tak sadar pun, mereka tetap menjagamu.”
Ghalib melanjutkan, “Ketika guci ini kuserahkan padamu, sepuluh ribu tentara pilihan dalam kendalimu juga. Pasukan alam gaib. Kau bisa menambahnya lagi jika kau rasa masih kurang.”
“Lalu kapan tugas itu selesai?”
“Sampai seseorang muncul. Ia kelak mendampingimu. Tetapi ada satu persyaratan lagi yang harus terpenuhi untuk menuntaskan tugas itu. Aku akan menemuimu lagi,” kata Ghalib sambil menyerahkan guci kecil itu.
“Dia, manusia atau jin?”
“Manusia.”
“Perempuankah?”
Tak ada jawaban. Ia ingin bertanya lagi, tapi ia tak teruskan ketika menyadari tiba-tiba tubuhnya telah berbaring di tempat tidur di kamarnya. Di tangannya tergenggam guci kecil dari tembikar. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)