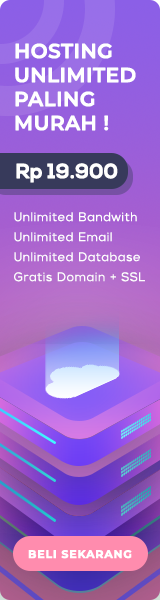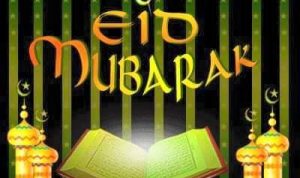Dua juwita, satu gadis satunya janda, membuat Ampenan seperti tersiram minyak wangi, semerbak hingga melewati tapal batas.
Kathelijn Monique kini lebih sering bersama Cornelia di waktu sore. Ia bercengkerama di berugaq, dan menemani Cornelia yang melatih anak-anak dan para remaja bermain musik. Janda itu ternyata memiliki suara cukup bagus. Setiap ia menyanyi, semua tertegun. Para pemain gasing menghentikan permainan mereka.
Kini di sekitar arena permainan gasing lebih ramai. Jalan pinggiran Sungai Jangkok nyaris tertutup setiap sore. Orang-orang memadati area pojok ujung jembatan Ampenan yang tak seberapa luas, kini terasa semakin sempit.
Jago-jago gasing kini tidak saja berdatangan dari seluruh penjuru Ampenan. Setiap hari terus bertambah. Datang dari Dasan Agung, Kekalik, Sekarbela, Pagutan, Pegesangan, bahkan Cakranegara.
Main gasing dengan motif midang (mengapeli). Kehadiran dua wanita jelita itu, membuat hampir semua pengunjung menjadi sangat royal. Makanan dan minuman para pedagang di lokasi itu selalu habis.
“Silaq pade pesen kupi, laun tiyang bayahan (silakan semua pesan kopi, nanti saya yang bayar),” kata Miaseh, saudagar ayam dari Dasan Agung.
“Jaje, bait jaje-jaje sino. Besuh-besuh. Adeq pade betenage tabegasingan (jajan, ambil kue-kue itu. Kenyang-kenyang. Supaya semua bertenaga bermain gasing),” Sapoan, pandai emas dari Sekarbela unjuk keroyalan, sambil mencuri pandang menatap Kathelijn dan Cornelia yang duduk di berugaq.
Lagak para dermawan dari luar wilayah itu sangat membuat dongkol tiga lelaki yang sedang minum kopi. Mereka adalah Abah Karim, Daeng Salam, dan Babah Hongli.
“Lama-lama kita diampahin (diremehkan) para pendatang baru ini,” ucap Abah Karim.
“Jangan sampai kita semakin tenggelam, akhirnya dilupakan,” menyahut Daeng Salam.
“Ini wilayah kita. Kita harus bikin aturan,” tegas Babah Hongli.
Tiga orang yang selama ini tak pernah akur, kini terlibat mufakat yang serius. Ternyata rasa sebal, kekhawatiran kehilangan pamor, membuat mereka bersatu-padu.
“Abah duluan maju,” kata Daeng Salam.
Suara Abah Karim yang terdengar keras dan berwibawa, menghentikan keriuhan di seputar gelanggang.
“Sahep-sahep, saudara-saudara semua. Ana sita waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal penting. Walaupun agak telat, ana dan sahep-sahep yang telah merintis gelanggang gasing ini, mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengunjung dari luar Ampenan. Kami sangat bangga dan gembira. Kini arena kita sudah dikenal luas, dari Ampenan hingga Cakra,” katanya memulai.
“Karena sudah menjadi arena yang bukan hanya digunakan bagi warga Ampenan, kita harus mulai berpikir untuk perkembangan arena ini selanjutnya. Ana persilakan sahep ana, yang ana anggap seperti saudara sendiri, memberikan beberapa arahan untuk kepentingan kita bersama. Silakan, Daeng Salam!” Abah Karim menutup sambutannya.
Daeng Salam terkesima mendengar namanya disebut Abah Karim. Baru kali ini lelaki itu menunjukkan hal yang simpatik, yang membuatnya merasa terhormat di depan ratusan pasang mata. Sebelumnya ia mendehem-dehem, menyingkirkan dahak yang menempel di tenggorokannya.
“Terima kasih, Abah Karim. Tokoh Ampenan yang sangat saya hormati, saya juga menganggapnya abang sendiri,” ucap Daeng Salam, “Saudara-saudara. Ampenan adalah kota kebanggaan kita. Kota yang dihuni banyak suku bangsa, tak kalah dengan Batavia dan Surabaya. Kota yang sangat saya cintai, sampai saya hampir melupakan kampung halaman sendiri.”
Gemuruh tepuk tangan menimpali kalimat yang dilontarkan Daeng Salam. Ia melanjutkan kembali, “Ampenan telah lama terkenal menjadi pintu masuk orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang tinggal di kota ini hidup rukun, menjunjung kebudayaan yang sudah berlangsung sejak lama. Terciptalah kedamaian dalam peradaban yang terpelihara. Seperti pepatah Minang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Begitulah kita hidup di sini selama ini. Siapa orang-orang Minang di sini?”
Beberapa orang mengangkat tangan.
“Permainan gasing adalah salah satu kegiatan mempererat silaturrahmi. Kami ingin memperluas ikatan persaudaraan itu dengan memusatkannya di Ampenan. Persaudaraan aneka suku-bangsa dari Ampenan hingga Cakranegara, bahkan tidak menutup kemungkinan silaturrahmi se-Pulau Lombok. Bagaimana saudara-saudara?”
“Setuju! setujuuuuu!”
“Untuk lebih detilnya perencanaan kita, mari kita dengarkan penjelasan sahabat dan saudara kami yang juga perintis gelanggang. Kepada Babah Hongli, kami persilakan.”
Babah Hongli maju menggantikan Daeng Salam. “Saudara-saudara, kami sudah sering mengadakan perlombaan di tempat ini. Lomba tingkat Ampenan. Dengan hadirnya saudara-saudara dari luar wilayah, kami mengusulkan pertandingan dengan skala yang lebih luas, dengan peserta dari Ampenan hingga Cakranegara.”
“Setujuuuuu!”
Naluri dagang Babah Hongli seketika muncul. Ia ingat seorang familinya di Cakranegara. “Kita perlu punya busana khusus untuk para peserta. Ada juga biaya pendaftarannya. Nanti soal tempat mendapatkan pakaian dan berapa harganya saya sampaikan dalam dua-tiga hari mendatang. Yang penting kita sepakat dulu tentang rencana ini. Kita tentukan waktunya. Sekian dan terima kasih.”
“Untuk biaya pakaian saya akan tanggung separuh, dan bagi yang kurang mampu biar saya yang talangi uang pendaftarannya,” terdengar sebuah usul dari Sapoan yang disambut tepukan tangan.
“Hadiahnya saya tanggung untuk sepuluh pemenang. Tentukan saja berapa dan apa jenis hadiahnya,” Miaseh tak mau kalah soal andil.
“Orang-orang hebat!” terdengar seruan Kathelijn dari arah berugaq. Suara yang di telinga para pengusul kegiatan begitu merdu, membuat dada mereka terasa seperti tersiram percikan surga.
“Siapa dulu Abah Karim, Daeng Salam, dan Babah Hongli. Juga semua pihak yang telah berbuat untuk kemajuan di arena ini. Orang-orang yang istimewa,” Cornelia ikut mengomentari.
Suara dua bidadari. Menenteramkan perasaan. Suara bening yang melenyapkan debu-debu Ampenan. Debu-debu di hati.
Tiga lelaki itu, Babah Hongli, Daeng Salam, dan Abah Karim begitu lega. Mereka berdiri tegak, mengangkat pundak. Lubang hidung mereka bertambah mekar. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)