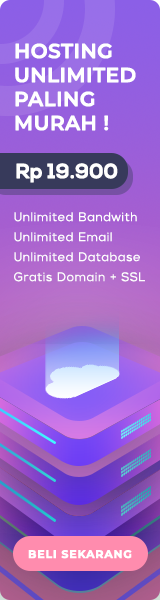“Waktuku tidak lama, Ahmad,” Ghalib mengingatkan. Ia kembali memejamkan mata. Dadanya turun-naik seperti sukar menghela dan menghembuskan nafas.
Akhirnya terdengar juga suara yang ditunggu-tunggu. Awalnya Ahmad bicara pelahan. “Berat bagi saya memulai mengucapkannya. Jauh lebih berat dibanding ketika saya melaksanakan ujian tiga hari tiga malam saat pertama berjumpa Kakek Ghalib di tengah rimba. Dan jauh lebih berat jika dibandingkan saat-saat saya diburu dan ingin dibinasakan lantaran benda yang diberikan Kakek Ghalib kepada saya. Saya hanya tak ingin menyederhanakan cinta seperti terdefinisi dalam terminologi Yunani Kuno. Mulai Storge, Philia, Pragma, sampai Philautia. Seperti Eros yang menerjemahkan cinta hanya hasrat seksual dan sesuatu yang erotis. Klaim-klaim yang akhirnya menganggap enteng kisah cinta dari belahan dunia lain. Bahkan menafikan percintaan Adam dan Hawa yang terusir dari surga lantaran kobaran dan emosi kuat yang muncul dari perasaan cinta. Saya tak ikut-ikutan mendefinisikan cinta sebab dengan begitu saya membuatnya menjadi sempit.”
Hening sesaat. Ahmad mengusap wajahnya yang berkeringat. “Kata-kata menjadi tiada berkekuatan dan kehilangan makna karena seringkali tidak dibuktikan dengan tindakan. Inilah yang membuat saya sampai saat ini belum berani mengungkapkannya kepada Cornelia. Saya ingin mendahuluinya dengan sikap dan perlakuan. Saya tak ingin pada suatu ketika dikatakan pendusta,” ucap Ahmad, “Orang Sasak tak mengenal kata cinta. Tapi ia nyatakan itu dengan tindakan. Membawa lari perempuan yang dikasihinya dengan segala risiko yang bakal dihadapinya, juga kemungkinan kehilangan nyawa. Nelayan-nelayan di lautan Ampenan setiap hari berhadapan dengan maut. Mereka pun tak pernah mengumbar kata cinta, tetapi keberanian mereka adalah perwujudan cinta sesungguhnya yang melahirkan tekad dan tanggungjawab. Para kuli pelabuhan bertelanjang dada menantang matahari. Terik yang membakar kulit tak mereka rasakan sebab mereka berada di sana karena tanggungjawab dalam cinta.”
“Cornelia,” sambungnya, “Aksara tak bisa mewakili ungkapan cinta. Juga lukisan, alunan musik, dan benda-benda berharga. Cinta bagi saya sesuatu yang tak ternilai. Allah mempertemukan saya dengan kamu, melalui tangan-tangan yang kehendaki-Nya. Melalui perantara Kakek Ghalib, aroma, atau apa saja. Tetapi, saya merasa belum pantas mencintai kamu.”
Peluh Ahmad semakin membanjiri tubuhnya. “Cornelia dengan pesona keanggunannya, membuat saya sangat tahu diri. Belum banyak yang bisa saya berikan dan lakukan untukmu. Tetapi jika Cornelia mempercayai saya, ijinkan saya berjanji.”
“Lanjutkan, Ahmad,” kata Ghalib dan Cornelia bersamaan.
“Orang-orang Ampenan menyayangi Cornelia. Dia tidak dianggap orang asing. Ada banyak yang menangis ketika ia menghilang. Ribuan orang mencarinya. Ribuan orang tak ingin kehilangannya. Saya berjanji melindungi orang-orang Ampenan seumur hidup saya, karena perhatian mereka kepada wanita yang sangat…”
“Sangat apa, Ahmad?” Cornelia tak sabar.
“Wanita yang sangat saya cintai. Dia, Cornelia!”
“Ahmad!” pekik Cornelia tak dapat menahan perasaannya. Air matanya tumpah, haru karena bahagia.
Dan ia merasa telah mencapai kulminasi, seperti klimaks di malam pertama sepasang pengantin, ketika pemuda itu melanjutkan kalimatnya.
“Demi Allah, saya mencintaimu, Cornelia. Saya ditakdirkan jatuh cinta kepadamu. Anugerah terindah Ilahi. Cinta di atas segala kata, segala puisi, segala isyarat, dan segala perumpamaan yang mengatasnamakan cinta.”
Untuk pertama kalinya Ghalib tersenyum. Wajah tua itu bercahaya. Air matanya pun mengalir. “Ahmad, seperti kukatakan, aku tak pernah mendapat anugerah perasaan cinta. Tetapi ucapan-ucapanmu, membuatku dapat merasakannya. Aku berterima kasih pada kalian. Sesungguhnya, inilah saat yang kutunggu-tunggu. Aku lega, selega-leganya. Ketahuilah, saat ini juga berakhir sudah tugasmu, Ahmad. Kini, pohon purba itu tak perlu kau jaga. Juga tak butuh lagi perlindungan segala makhluk itu. Mereka akan segera pergi.”
“Mengapa demikian, Kakek?”
“Karena kekuatan cinta menjaganya hingga kiamat nanti. Kumohon kalian senantiasa mempertahankan kesejatian cinta yang juga berdampak untuk kemaslahatan manusia dan bermacam makhluk ciptaan-Nya.”
Pertapa itu merogoh saku jubahnya.
“Hanya ini yang bisa kuberikan padamu, Gadis. Sudah seribu tahun kusimpan. Pakailah,” Ghalib menyerahkan sebuah gelang emas murni bertatahkan mirah delima kepada Cornelia. Sekitar pelataran itu menjadi silau berbaur cahaya kemerahan.
Ghalib memberi isyarat kepada Cornelia dan Ahmad agar mendekat. Ia mencium kening keduanya. “Waktuku telah tiba. Dari Pegunungan Anatolia di Turki, Sungai Tigris membelah Mesopotamia yang bermuara di Teluk Persia. Di situlah aku dilahirkan. Kini ajalku di sungai juga, walaupun bukan di negeri kelahiranku. Di Sungai Jangkok ini, di akhir hayatku, aku temukan kebahagiaan itu. Ternyata pilihanku tak salah ketika berusaha mempertemukan dua jiwa. Dua jiwa yang punya banyak persamaan. Kalian manusia-manusia yang tak mementingkan diri sendiri. Yang sangat membagiakanku, kalian saling mencintai. Pesanku, pada malam 17 Ramadhan nanti, sempatkan memandang ke arah pohon itu. Betapa aku mengagumi seorang lelaki agung, manusia pilihan Penguasa jagat raya. Lelaki pembawa pencerahan, sejak ia mendapat wahyu pertama. Sebaris firman yang begitu luas maknanya di ayat pertama. Diturunkan dari lauhul mahfuzh ke baitul izzah, langit dunia. Baca, baca, dan bacalah, itulah yang terus kuamalkan, kupelajari. Semakin aku mengerti, semakin aku merasa betapa ilmu-ilmu yang kumiliki hanya noktah kecil di samudera pengetahuan-Nya. Ingat-ingat pesanku. Pandang dari arah mana saja. Ada sesuatu yang muncul di sana yang bisa kalian baca.”
Itulah kalimat terakhir sang pertapa. Setelah ia ucapkan itu tangannya terkulai di atas pangkuannya. Matanya terpejam tapi bibirnya membentuk seulas senyuman. Sang pertapa pergi untuk selama-lamanya.
Ahmad dan Cornelia memeluk lelaki tua itu. Air mata mereka bercucuran, merasa sangat kehilangan. Ahmad membaringkan tubuh itu di lantai. Tetapi tak lama kabut tebal muncul, membungkus tubuh renta itu. Kabut lenyap, tubuh Ghalib turut menghilang.
“Ahmad, saya sangat bahagia, tapi juga sangat sedih. Saya sangat berduka atas kepergiannya. Saya akan selalu mengenangnya,” kata Cornelia sambil mengusap air matanya.
*
“Kita pulang sekarang,” ajak Ahmad.
“Tapi saya tak mau kamu senggeq lagi.”
“Kenapa?”
“Saya mau kamu gendong.”
“Kamu sudah besar, tidak malu digendong?”
“Saya kekasihmu. Ingat kata-katamu tadi.”
“Memangnya saya sudah ngomong apa tadi?”
“Kamu ini bikin saya kesal,” gadis itu merajuk.
Akhirnya ia digendong juga. Tangan kiri Ahmad menahan bagian leher, dan tangan kanannya di lipatan kaki gadis itu.
“Kita tidak usah lewat titian itu lagi,” kata Ahmad.
“Memangnya kamu mau menyeberangi sungai membawa saya?”
“Iya.”
“Kamu nanti basah kuyup.”
Dan Ahmad benar-benar masuk ke dalam sungai, menuju tepian tempat berugaq berada. Dari sisi pelataran air sungai hanya sebatas pinggang. Tubuh gadis itu ia angkat lebih tinggi agar tak tersentuh air.
“Astaga, Ahmad, benaran kamu? Kamu bisa kedinginan, bisa masuk angin,” kata gadis dalam gendongan itu khawatir.
“Hanya air sungai. Anggap saja sungai cinta.”
“Andaikata di bawahmu itu bara api, kamu masih tetap menggendong saya, Ahmad?”
“Saya terus berjalan menggendongmu.”
“Kamu tidak rasakan panas?”
“Tidak. Itu ‘kan panas api cinta.”
Gadis itu tertawa senang.
Ahmad telah tiba di tepi sungai, tapi ia masih terus menggendong gadis molek itu.
“Sampai berugaq itu turunkan saya, Ahmad. Nanti dilihat Willem dan Rabiyah.”
“Takut, ya?”
“Malu, Ahmad. Semakin ada bahan mereka meledek saya.”
Tiba di depan rumah Cornelia mengetuk pintu. Rabiyah muncul disusul Willem. Mereka terheran-heran melihat celana Ahmad basah kuyup.
“Tak ada hujan, kenapa bisa basah, Ahmad. Kamu ngompol, ya?” tanya Rabiyah.
“Tadi didorong Cornelia.”
“Bohong! Dia terpeleset lalu tercebur di sungai,” sergah gadis itu.
“Malam-malam kalian main di sungai?” Willem tambah heran.
Ahmad pamit. Embun mulai turun. Di langit, rembulan belum jua muncul. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)