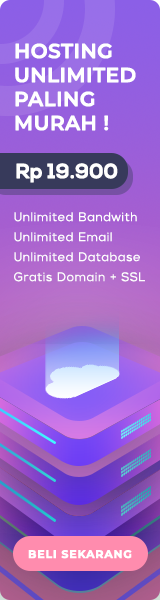BERBAGI News – Gadis itu tak dapat menahan luapan perasaannya. Di depan ribuan pasang mata ia benamkan wajahnya di dada Ahmad. Dipeluknya pemuda itu erat-erat, seperti tak ingin ia lepaskan.
Aula seperti meledak dengan gemuruh tepuk tangan. Para hadirin berdiri lantaran terpesona. Penampilan sepasang kekasih itu membuat mereka tak henti-hentinya bergumam kagum.
“Suaramu bagus, Ahmad. Saya tak sangka. Lagu itu melankolik, tentang romantisme yang sebenarnya belum pantas dinyanyikan orang seusia kita. Tetapi saya suka, Ahmad. Sangat menyentuh. Saya ingin kamu menyanyi lagi, sayang,” gadis itu mempererat pelukannya. Tepuk tangan semakin bergemuruh.
“Maafkan saya, Cornelia. Tidak akan ada lagu ke dua, ke tiga, dan seterusnya. Saya beranikan diri menyanyi, karena hari ini milik kamu, secara khusus dipersembahkan untukmu.”
Saat ia kembali dipersilakan maju untuk memberikan nama taman dan istana itu, Cornelia menyebut Ampenan de Stad van de Liefde. Baru saja ia menyatakannya, sebuah prasasti marmer berukuran sangat lebar terpampang di depan hadirin, bertulis besar-besar kalimat itu yang jika diterjemahkan adalah Ampenan Kota Cinta!
Usai acara, bersama Ahmad ia memeriksa seluruh kamar hingga lantai atas.
“Ahmad, kita punya bangunan dan tempat yang indah ini. Mengapa kita tidak tinggal di sini sekalian?”
“Kita tidak akan betah.”
“Mengapa?”
“Karena bukan alam kita. Juga karena manusia punya sifat cepat bosan.”
“Saya tidak cepat bosan. Kamu besok-besok mungkin akan bosan pada saya, Ahmad? Apalagi kalau saya nanti sudah tua.”
“Cinta membuatmu tetap cantik, Cornelia.”
“Lalu kebosanan yang kamu maksud bagaimana?”
“Saya tanya dulu, apakah kamu merasa lelah sejak berada di sini?”
“Tidak.”
“Nah, itulah salah satunya yang cepat membuat bosan. Di alam dimensi kita, orang butuh capek agar ketika santai ia menikmatinya,” kata Ahmad. “Kesenangan itu harus ada perbandingannya, sehingga bisa ternikmati. Itu artinya seseorang mesti berpayah-payah agar bisa menghargai sesuatu anugerah. Berlapar-lapar dulu, maka ketika mendapatkan makanan yang sederhana pun terasa nikmat. Merasakan kepahitan baru tahu sesuatu yang manis. Kalau terus-terusan senang, maka timbul kebosanan, berusaha mencari kesenangan yang baru. Dari sinilah petaka muncul. Orang miskin kepingin kaya, itu wajar. Tetapi sesudah kaya lalu mau lebih kaya lagi dan menghalalkan segala cara untuk tujuan itu, maka bencana muncul.”
“Sama juga ketika sudah punya istri, kepingin nambah lagi. Begitu, Ahmad?”
“Saya tidak mengatakan itu.”
“Kamu harus janji, Ahmad, sebelum kamu menikahi saya.”
“Janji apa?”
“Pura-pura bodoh lagi. Kamu tidak mencari perempuan lagi setelah menikahi saya.”
“Kenapa kamu anggap saya rakus perempuan? Apa saya punya tampang seperti itu?”
“Mungkin,” gadis itu cemberut.
“Tak baik selalu memelihara kecurigaan, memelihara prasangka-prasangka. Saya berdoa Tuhan terus menambah cinta itu, sehingga saya setiap hari jatuh cinta kepadamu.”
“Sampai sekarang kamu setiap hari jatuh cinta kepada saya?”
“Setiap menit.”
“Bohong!”
Mereka meninggalkan istana, menuju bagian taman yang belum mereka kunjungi.
“Kamu benar, Ahmad. Lama-lama jenuh juga di sini. Bawa saya kembali ke alam nyata.”
“Baik, kita juga sudah cukup lama di sini.”
Dalam satu tarikan nafas mereka kini berada di tengah-tengah aliran Sungai Jangkok.
“Di sini saya baru merasa lapar, Ahmad. Tapi saya tak mau pulang dulu. Saya juga tak mau kamu mengandalkan kemampuanmu. Kamu akan bisa hadirkan apa pun permintaan saya secara gaib. Saya ingin saat ini kamu jadi orang biasa. Bersusah payah mencarikan makanan apa saja, lalu kita mendapatkan kenikmatan seperti kamu bilang.”
“Saya tidak pernah inginkan semua yang ada pada saya itu, Cornelia. Semuanya datang dan terjadi begitu saja. Tapi saya setuju dengan keinginanmu itu. Mari kita cari makanan di sungai ini.”
Hari belum terlalu siang, namun matahari cukup menyengat. Ahmad mengajak Cornelia ke tepi sungai di sebelah selatan. Di sebatang pohon pisang ia mengambil serat pelepahnya yang seperti benang.
“Untuk apa?”
“Saya akan menunjukkan padamu cara menangkap udang. Kita cari lagi lidi daun kelapa.”
Di ujung lidi itu Ahmad membuat lingkaran berdiameter sekitar dua centimeter dari serat batang pisang. Pangkal lingkaran itu lalu diikat dan disimpul.
“Kita buat satu lagi. Waktu kecil saya banyak habiskan waktu di sungai menangkap udang.”
Mereka kembali ke sungai. Ahmad memberi contoh menangkap udang menggunakan joran lidi dan serat batang pisang tersebut.
“Nah, lihat udang di dekat batu itu. Dekatkan ke matanya. Tarik begitu kena.”
Seekor udang sebesar telunjuk berhasil ditangkap. Cornelia bersorak kegirangan. Ia mencoba melakukannya sendiri. Tak lama terdengar lagi teriakannya. “Dapat, Ahmad. Dapat!”
Selama lebih dua jam mereka keasyikan di sungai, sampai Cornelia tak merasakan terik matahari membuat kulitnya memerah. Mereka telah mengumpulkan lebih dari seratus ekor udang hasil tangkapan.
“Sudah cukup banyak, kita bakar sekarang.”
“Di sana saja, dekat berugaq kita,” Cornelia mengusulkan.
“Sebentar saya cari bahan pembuat api.”
Di dekat berugaq Ahmad memutar sebatang ranting dengan kedua telapak tangannya. Di bawah ranting itu terdapat sepotong kayu. “Gesekan kayu dengan kayu secara terus-menerus ini akan mengasilkan panas dan menjadi bara api,” jelasnya.
Asap mulai keluar dari ujung ranting yang menggesek kayu di bagian bawah. Bara api kecil hasil gesekan itu diletakkan di segenggam rumput kering. Ahmad meniupnya. Tak lama api menyala. Terdengar lagi seruan Cornelia.
“Ini bukan intervensi makhluk gaib, ya?”
“Semua orang bisa melakukannya.”
Kayu-kayu kering segera disusun di atas api. Tak lama api semakin membesar. Ahmad menusuk udang-udang itu dengan lidi dan memanggangnya di atas bara api. Setelah matang ia berikan kepada Cornelia. Ia memanggang lagi.
“Luar biasa. Ini benar-benar nikmat. Saya tidak pernah makan udang segurih ini. Kamu coba,” Cornelia memasukkan sepotong udang ke mulut Ahmad.
“Nikmat karena kamu merasakan lelah menangkapnya.”
“Besok kita cari lagi, Ahmad.”
Tidak mereka sadari, Rabiyah muncul di belakang mereka yang sedang duduk berjongkok menikmati udang-udang Kali Jangkok yang telah dibakar.
“Astaga, di sini kalian? Kapan pulang? Aduh, kenapa kalian seperti anak kecil. Kulit Non Lia sampai merah-merah begitu. Itu muka Non hitam bekas arang. Masuk, masuk, Non. Inaq mandikan sekarang.”
“Sebesar ini, Cornelia masih dimandikan?” timpal Ahmad.
“Bohong inaq, Ahmad. Jangan percaya.”
“Benar, Ahmad. Besok itu kerjaanmu, menggendongnya setiap hari ke kamar mandi. Menyabuni dan menggosok badannya. Memandikannya, seperti bayi,” kata Rabiyah lagi menggodanya. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)