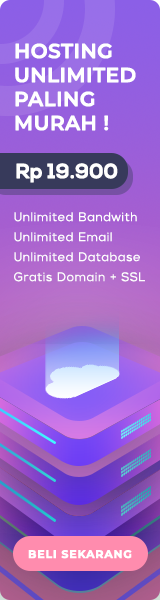BERBAGI News – Willem pamit ke Batavia. Ia berencana selama dua bulan berada di sana. Pagi-pagi saat ia berkemas-kemas, ia menyindir dan menggoda Cornelia habis-habisan.
“Inaq, apa saya salah dengar, orang itu ngotot ingin saya bawa pergi dari Lombok, waktu dia sakit tempo hari,” kata Willem.
“Tuan Muda tidak salah. Saya juga dengar.”
“Kenapa sekarang dia tidak mau ikut ke Batavia?”
“Bosan saya dengar dari tadi. Apa tidak ada bahan lain kalian bahas? Willem, cepat ke pelabuhan, nanti terlambat. Inaq tidak usah tanggapi Willem. Dia harus cepat ketemu tunangannya di Batavia. Sudah lama saya rindukan keponakan. Ayo kita antar dia,” sahut Cornelia.
Di depan terdengar ketukan pintu.
“Masuk, Ahmad,” kata Rabiyah.
“Nah, kau harus dengar cerita ini, Ahmad,” Willem mengulangi lagi kalimatnya tadi.
“Itu lagi, itu lagi! Jangan dengarkan, Ahmad,” seru gadis itu setengah berteriak.
Dua buah dokar mengantar mereka ke pelabuhan. Willem berpesan kepada Ahmad agar lebih sering melihat keadaan rumah selama ia pergi.
“Jaga adik saya, Ahmad. Saya cukup lama di Batavia,” pesannya.
Kapal uap SS Van Swoll membawa Willem menuju Batavia. Sebuah kapal penumpang berkapasitas 1.238 orang yang beroperasi di perairan Hindia Belanda sejak 1930.
Cornelia memandang kapal itu, sejak meninggalkan Pelabuhan Ampenan, hingga berupa noktah kecil di tengah samudera.
“Dia pergi, satu-satunya keluarga saya di sini. Sekarang saya baru sadar, saya orang asing yang sendirian di sini,” kata Cornelia. Kedua matanya menatap sendu.
“Mengapa kamu menganggap diri asing? Apakah kamu ingin mengatakan, hubungan saya denganmu menjadi penyebab kamu terpisah dengan keluargamu?”
“Saya tidak menyebutkan itu, dan tidak ada kaitannya dengan hubungan kita. Hanya saya cukup bersedih saat ini. Satu-persatu orang-orang yang saya sayangi, menjauh bahkan meninggalkan saya. Mulai dari kepergian ibu saya. Lalu kami meninggalkan negeri kelahiran kami. Ayah saya kembali ke Eropa. Sekarang Willem pergi jauh, walaupun hanya untuk beberapa lama. Saya tidak sanggup membayangkan ketika kamu juga meninggalkan saya.”
Ombak Pantai Ampenan berdebur keras. Angin cukup deras bertiup dari arah barat. Sepasang kekasih itu masih berdiri tak jauh dari dermaga, memandang ke arah gelombang yang datang susul-menyusul. Beberapa saat mereka berdiam diri.
“Kamu nampak bersedih, Cornelia. Apa yang bisa saya lakukan untukmu?”
Gadis itu tak menjawab. Ia menekuri pasir pantai, menggurat pasir yang basah dengan ujung jempol kakinya.
“Saya mungkin bisa memindahkan mega-mega untuk memayungimu, ketika kamu terancam terik matahari yang membakar,” Ahmad berhenti sesaat. “Tapi saya lebih tak tahan melihatmu seperti ini. Saya tak membiarkan senyum itu hilang dari wajahmu.”
“Ahmad, kamu kadang-kadang seperti penyair,” sebuah senyum merekah di bibirnya, seperti kelopak mawar layu yang tiba-tiba segar lagi. “Tapi apa yang kamu lakukan kalau saya…”
Tiba-tiba gadis itu berlari menyongsong gelombang yang datang cukup tinggi. Ia hilang tergulung gelombang. Tetapi kesigapan Ahmad lebih cepat dari tarikan gelombang yang hendak menyeret ke tengah lautan. Ia menangkap tubuh molek itu, menggendongnya menepi.
“Saya takkan membiarkan gelombang menjamahmu sekehendaknya.”
Cornelia memejamkan mata. Ia nikmati setiap langkah Ahmad membawanya ke tepian. Ia nikmati degup jantung pemuda yang menempel di tubuhnya. Tetapi deburan di dadanya sendiri lebih dahsyat daripada gemuruh gelombang dan ombak yang tadi sempat menerjang tubuhnya.
Sepasang kekasih menjauh dari pantai. Tetesan air berjatuhan dari tubuh mereka, lenyap di butir-butir pasir kering. Tubuh-tubuh yang kuyup lantaran terkaman gelombang yang tak mampu menyeret mereka. Tetapi hanya satu pusaran arus yang sanggup menenggelamkan. Pusaran kuat di tengah-tengah samudera cinta.
*
“Inaq, puasa itu berapa lama?”
“Sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam.”
“Sebulan penuh?”
“Iya.”
“Saya ikut puasa, Inaq.”
“Benar, Non?” Rabiyah menatap gadis itu seperti tak percaya. “Non Lia disuruh Ahmad?”
“Tidak. Niat saya sendiri.”
Esoknya, sejak awal Ramadhan, gadis Eropa itu mulai berpuasa. Puasa untuk pertama kalinya. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)