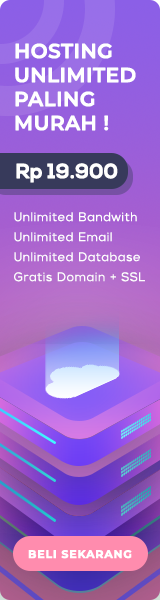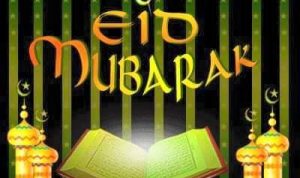BERBAGI News – Sambil menyelam minum air. Taktik inilah yang digunakan militer Jepang dalam menghadapi Belanda di wilayah koloninya. Selain pertempuran fisik, di daerah-daerah yang secara teritorial tidak dalam pengawasan ketat, disusupi para opsir Jepang yang menyaru sebagai pedagang atau penjual jasa, sambil menebar propaganda.
Di kawasan Cakranegara bermunculan pedagang yang menjual barang-barang dengan harga sangat murah. Mulai dari peralatan pertanian hingga perabotan rumah tangga.
Di awal 1942, masyarakat Lombok mulai mengenal produk-produk Jepang.
Toko Miyore di Cakranegara, salah satu tempat penjualan produk Jepang. Toko ini menjual sepeda yang dapat diperoleh dengan pembayaran tunai bahkan kredit. Salah satu sepeda bermerek Maruishi, jenis sepeda jengki yang sudah diproduksi sejak era Meiji di Jepang.
Pribumi awalnya sulit membedakan mana orang Tionghoa mana Jepang. Mereka sama-sama berkulit kuning dengan mata yang sama sipit. Namun perbedaan mulai diketahui dari intonasi atau logat saat bicara.
“Sepeda buatan mana, Koh?” seorang warga dari Kampung Banjar datang ke toko itu.
“Buatan Jepang.”
“Kuat, Koh?”
“Barang buatan Jepang terbaik dan paling murah di dunia.”
“Murah?”
“Sangat murah, dan bisa dicicil,” pemilik toko menyebutkan harga.
“Saya beli sekarang juga, Koh. Tunai.”
“Karena kamu pembeli pertama, saya kasih separuh harga.”
“Hah?”
“Jangan panggil Koh. Panggil saya Hachiro-san atau Saudara Tua saja.”
“Saya dengar Jepang sedang perang lawan Belanda.”
“Jepang akan mengusir orang-orang Eropa dari seluruh Asia. Perang Jepang perang suci, demi kemakmuran Asia. Kedatangan Jepang akan membuat kehidupan lebih baik. Harga-harga stabil dan murah.”
“Terima kasih, Hachiro-san. Saya akan kabarkan ini. Saya akan beritahu siapa saja untuk datang dan belanja di toko ini.”
“Di sebelah juga ada toko kelontong. Semuanya barang Jepang. Silakan ke sana juga. Murah, murah sekali semuanya.”
Kabar murahnya produk Jepang dan begitu ramah dan bersahabatnya orang-orang dari Negeri Sakura kini menjadi perbincangan di mana-mana. Tak terkecuali di arena pegangsingan. Bahkan perkembangan perang Jepang melawan Belanda hampir setiap hari dihembuskan dari para opsir yang menyamar.
“Jepang sudah mengalahkan Amerika. Sekarang Belanda mulai terdesak.”
“Kalau Jepang menang, kita berganti penjajah?”
“Tidak. Jepang tidak menjajah. Mereka datang memperbaiki keadaan, menjadikan negeri kita adil dan makmur.”
“Mereka membantu kita menjadi negara merdeka, betulkah?”
“Tidak salah lagi. Mari kita tunggu kedatangan saudara-saudara tua kita.”
“Harga-harga akan segera turun.”
“Tidak akan ada perbedaan kelas lagi. Anak-anak semua bisa sekolah, bisa berhitung dan membaca.”
“Beras murah.”
“Minyak gas (minyak tanah) murah.”
“Kalau semua murah, ana bisa kawin lagi.”
“Ana juga.”
Di dalam rumah Willem juga tengah berlangsung pembicaraan sejak siang hari.
“Jepang dan Belanda bukan kali ini saja saling mengenal. Jauh sebelum ditandatanganinya Konvensi Kanagawa, Belanda satu-satunya pihak Eropa yang menjadi mitra dagang Jepang. Hubungan yang cukup akrab. Bahkan di abad 17 Belanda pernah mempekerjakan pasukan samurai Jepang di Maluku untuk melawan Inggris. Tapi sekarang hubungan itu berbalik,” ucap Willem. Wajahnya nampak kusut.
“Apa yang dirisaukan, Willem? Belanda di negeri ini punya pasukan dan peralatan tempur memadai,” sahut Kathelijn.
“Saya bimbang setelah serangan Jepang memporak-porandakan Pearl Harbor. Dan perlu diingat, pasukan mereka mendapat dukungan dari negara poros, yaitu Jerman dan Italia. Jerman sendiri belum meninggalkan negeri kita.”
Ruangan hening beberapa saat.
“Bagaimana selanjutnya, Willem? Kita tidak ada sangkut-paut dengan perang,” Cornelia membuka suara.
“Ingatlah dampak sebuah perang, Adikku. Kita harus membuat keputusan sebelum kemungkinan terburuk itu terjadi.”
“Maksudmu kalau Belanda kalah?” tanya Kathelijn.
“Kalau Jepang menang, kita ikut menjadi tawanan.”
“Kita hendak menyelamatkan diri ke mana, Willem?”
“Kita harus tinggalkan tempat ini.”
“Ke mana?”
Ruang kembali senyap. Cangkir-cangkir berisi air teh di atas meja sejak tadi belum tersentuh. Wajah-wajah tiga warga Eropa itu nampak muram. Benak mereka memikirkan hari-hari mendatang. Wajah-wajah penuh kecemasan membayangkan masa-masa suram. (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)