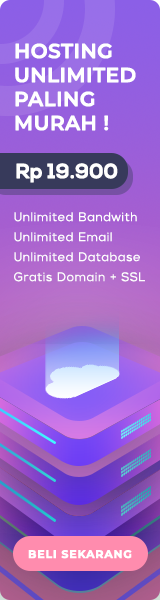“Ajak saya ke sana lagi. Ke tempat kita bertemu dengan Kakek Ghalib terakhir kalinya.”
“Mengapa tidak ke istanamu saja?”
“Setelah menikah kita ke sana.”
“Mengapa kamu tiba-tiba mengajak saya ke tempat itu sekarang?”
“Entahlah. Saya hanya kangen saja tempat itu. Saya ingat Kakek Ghalib. Saya ingat di situlah kamu mengungkapkan cintamu. Sejak itu pohon gaharu keramat itu kita tak perlu jaga lagi. Saya ingat kamu senggeq saya di titian itu. Pulangnya, kamu menggendong saya untuk pertama kalinya. Saya tiba-tiba ingat semuanya, Ahmad.”
“Bilang saja kamu kepingin di-senggeq dan digendong lagi. Dan apakah kamu ingin saya bicara tentang cinta lagi?”
“Setiap saat saya ingin kamu mengucapkan itu.”
“Saya khawatir kamu bosan. Sebab cinta itu bukan dijalani hanya dengan pengungkapan kata-kata. Bahkan jauh sebelum saya mengucapkan cinta kepadamu, saya sudah tunjukkan dengan sikap dan tindakan.”
“Saya tahu, Ahmad. Sampai sekarang kamu terus tunjukkan. Tidak pernah berkurang. Tapi, saya tetap butuh ungkapan lisan itu. Ucapan yang hanya untuk saya. Ingat, hanya untuk saya.”
Mereka telah sampai di pelataran itu. Aroma lembut harum gaharu menebar. Cornelia kembali hanyut. Ia pejamkan matanya.
‘Setiap menghirup aroma ini saya merasa damai, Ahmad. Aroma yang selalu menandai kehadiranmu. Kamu ingat waktu kita pertama kali berdua berada di atas jembatan ini?”
“Kapan?”
“Kamu tidak ingat, Ahmad? Jangan bikin saya gemas lagi.”
“Saya lebih ingat waktu kamu ingin membunuh saya di situ.”
“Saya jadi malu mengingatnya. Tapi mengapa kamu pasrah saja waktu itu?”
“Saya memang ikhlas, sebab saat itu saya benar-benar tahu semuanya.”
“Kamu mengetahui apa?”
“Saya tahu kamu benar-benar jatuh cinta kepada saya.”
“Kok cinta? Bukankah saya ingin mengakhiri hidupmu saat itu?”
“Itu karena kamu cemburu. Cemburu itu lantaran apa?”
“Kamu benar, Ahmad. Itu lantaran cinta.”
“Lihat pohon gaharu itu, Cornelia.”
“Iya, saya lihat. Kamu belum menceritakan waktu kamu memindahkannya ke sungai ini.”
“Kami memindahkannya dari lereng Rinjani, di hari kedatanganmu senja itu. Ketika kapalmu tiba. Saat pertama kali kamu menginjakkan kaki di Pulau Lombok.”
“Kamu tahu sejak pertama kali saya datang?”
“Udara Ampenan memberi kabar, manusia paling cantik pertama tiba di tempat ini.”
“Kamu berlebihan, Ahmad,” wajah gadis itu memerah. “Benarkah saya secantik itu, Ahmad?”
“Bukan hanya saya sendiri yang mengatakannya.”
“Mengapa kamu pindahkan?”
“Supaya saya tidak jauh-jauh lagi dari rumahmu. Saya awasi pohon itu sambil mengawasimu juga.”
“Baru kamu mengaku, ya? Pantas sejak awal di sini saya merasa dimata-matai.”
“Tapi kamu senang saya berada dekat-dekat sini, bukan?”
“Siapa bilang? Itu bukti kamu ternyata lebih cemburuan daripada saya. Kamu awasi, takut saya dilirik orang. Ngaku saja.”
“Iya, saya mengaku. Itu benar.”
Cornelia tertawa senang. Wajah cantiknya semakin bersinar.
Ahmad bercerita, selama tujuh tahun berturut-turut ia terus hidup dalam ketegangan. Dua misi sekaligus yang diembannya. Menjaga pohon purba di Rinjani dan guci tembikar yang selalu bersamanya. “Saya pertama kali bertemu Ghalib di usia 16 tahun. Sejak itu saya bolak-balik ke Gunung Rinjani. Sejak itu pula saya berurusan dengan ratusan manusia dari berbagai penjuru dunia. Manusia-manusia yang tak puas dengan kehidupan yang wajar.”
“Jika di hari yang sama saya bertemu beliau ketika saya berusia 13 tahun, berarti usia saya denganmu hanya selisih tiga tahun.”
“Artinya saya tidak terlalu tua untukmu, bukan?” kata Ahmad. Pandangannya tak beralih dari pohon purba di bawah jembatan. “Tahukah kamu, orang-orang dari bangsa mana yang saya hadapi selama ini?”
“Bangsa-bangsa non barat.”
“Saya tahu kamu pasti menjawab seperti itu. Sebab kamu yakin kebangkitan Eropa sejak renaissance di abad ke 16. Gerakan kebudayaan yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa di fase awal. Masa yang berlanjut ke abad pencerahan, Eropa yang modern. Eropa yang meninggalkan kepercayaan tradisional dan mitos-mitos. Benarkah? Saya bantah itu, berdasarkan pengalaman saya. Justru mereka yang paling banyak merepotkan saya.”
Cornelia mengerutkan kening.
“Isaac Newton seorang ilmuwan dari Inggris. Orang yang sangat rasional menurut kamu?” tanya Ahmad.
“Dia seorang filsuf, alkimiawan, matematikawan, fisikawan, dan ahli astronomi. Jelas, dia manusia logis.”
“Newton meninggal di usia 84 tahun. Setelah ia wafat di tahun 1726, di tubuhnya ditemukan sebagian besar air raksa. Temuan merkuri di tubuhnya diyakini sebagian orang sebagai konsekuensi studi alkimianya semasa ia hidup. Tetapi banyak orang tak tahu, Newton secara diam-diam mempelajari sihir dan cara pemujaan kepada setan. Namanya okultisme. Ia juga berupaya menemukan batu bertuah. Semua itu dilakukannya karena minatnya yang tinggi untuk dapat hidup abadi.”
Kini sepasang bola mata dara Eropa itu membesar.
Ahmad melanjutkan lagi.
“Jika tokoh cemerlang sehebat Isaac Newton seperti demikian, jangan kaget jika kenyataannya masih banyak orang barat irasional. Mereka yang takut mati, mereka yang ingin terus berkuasa selama-lamanya. Mereka mempelajari kitab Galdrabok yang berisi mantra-mantra empat penyihir legendaris Islandia. Ada pula The Black Pullet, kitab yang ditulis salah seorang prajurit Napoleon saat ia diselamatkan secara misterius. Sebuah manuskrip tentang pelajaran sihir. The Black Pullet kitab sihir Bangsa Prancis yang ditulis di abad 18. Dan jangan kira warisan penyihir abad pertengahan sudah raib dari Eropa. Penyihir-penyihir yang mempelajari The Sworm Book of Honorius, kitab yang mengajarkan cara memanggil iblis dan roh ini, berkali-kali menggempur saya.”
“Setelah mereka tahu ada yang lebih dahsyat daripada sihir yang mereka pelajari, mereka ke mari dan memburumu?”
“Begitulah. Tapi kita kini cukup lega.”
“Setelah Kakek Ghalib mendengar pengakuan cinta kita, pohon itu tak perlu kamu jaga lagi. Sebegitu dahsyatnya kekuatan cinta bisa melindungi pohon itu dari segala gangguan. Kamu bisa jelaskan, Ahmad?”
“Entahlah. Ghalib juga tak menjelaskan itu. Yang saya tahu, setelah kita penuhi persyaratan itu, pohon purba itu kembali ke asalnya.”
“Ke sungai ini?”
“Kita melihatnya di sini, tapi sebenarnya pohon itu telah berada pada dimensi lain, yang satu makhluk di dimensi mana pun tak bisa menembusnya. Kecuali atas perkenan Sang Pencipta jagat raya dan segala isinya. Pohon purba itu kini telah berada di langit ke tujuh yang berdekatan dengan surga. Akan selamanya aman di sana. Sebab ketika berada di bumi manusia cenderung menyalahgunakannya.”
“Tapi kamu tetap menjadi buruan, Ahmad. Benda itu ada padamu. Saya selalu mengkhawatirkanmu, Ahmad. Sampai kapan ini berakhir?”
“Kita serahkan kepada Tuhan. Pasti akan ada akhirnya.”
“Kita pulang, Ahmad. Gendong lagi, ya? Sampai rumah.”
“Kamu tidak malu lagi? Nanti dilihat Rabiyah. Kamu kena olok lagi.”
“Sudah tebal telinga saya diolok-oloknya. Ayo, gendong!”
Sambil berjalan Ahmad berkali-kali berpesan agar Cornelia berhati-hati. “Kamu jangan ke luar rumah lagi. Ingat kejadian beberapa hari lalu. Atau kamu mungkin perlu tempat sementara,” ucap Ahmad.
“Tidak usah, Ahmad. Saya akan berhati-hati, berada di dalam rumah terus. Saya akan ke luar kalau kamu datang.” (Buyung Sutan Muhlis/Bersambung)