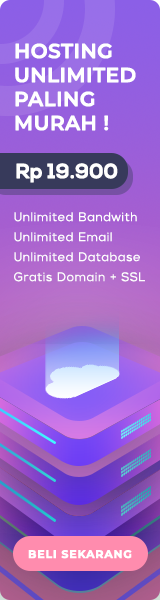Oleh : Firdaus Abdul Malik, Mahasiswa Sosiologi Universitas Mataram
BERBAGI News – Sudah banyak suara publik yang risih dengan munculnya tren selfie di lokasi bencana. praktik swafoto yang dilakukan oleh beberapa orang ketika ada bencana di daerah. Contohnya ketika gempa yang melanda Lombok Utara 2018 dan bencana-bencana lain nya.
Mengapa orang selfie di tempat bencana? Fenomena tersebut tidak muncul begitu saja, namun dibentuk oleh tren gradual (berangsur-angsur sedikit demi sedikit) yang muncul dari pola pikir narsistik, salah satunya melalui swafoto modern. Selfie menempatkan fokus perhatian pada ”diri” yang berselfie dengan wajah sebagai simbol representasi. Konsekuensinya, diluar dirinya hanyalah aksesoris.
Dulu, di awal tren selfie muncul, kutukan sudah datang dari mana-mana sampai akhirnya yang mengutuk ikut selfie dan menjadikan swafoto sebagai suatu kondisi normal yang baru. Masyarakat kita udah menerima selfie sebagai salah satu style atau cara berfoto. Kita bisa lihat fakta ini di semua ruang, dari panggung politik sampai kamar mandi. Mengapa selfie di lokasi bencana menjadi problematik? Menurut saya kuncinya adalah pada problem moral dari selfie itu sendiri. Konteks bencana sebagai simbol derita hanya sedikit memperburuk kutukan.
Ekspektasi moral publik dalam kondisi bencana adalah siapapun manusia yang bukan terdampak bencana memberikan empatinya pada korban dan keluarganya. Dengan kata lain, fokus dan prioritas perhatian adalah pada mereka yang tertimpa, termasuk kerusakan yang dihasilkannya. Kerusakan yang tampak secara visual idealnya sudah cukup melahirkan empati.
Dengan praktik selfie di lokasi bencana, para pelaku menyerang kemapanan moralitas publik. Pelaku selfie bencana mengatakan bahwa dirinya penting, tanpa mengatakannya. Terlepas apakah sebenarnya peran dirinya memang benar-benar penting karena sebagai relawan atau aparat, misalnya.
Foto selfie terdiri dari foto wajah diri yang menjadi titik fokus kamera dan background yang penuh dengan makna simbolik. Sebenarnya, background ini berbicara lebih banyak ketimbang wajah karena background selalu berganti sehingga kaya interpretasi, sedangkan selfie wajah dari dulu ya itu-itu saja, monoton.
Sayangnya, interpretasi nilai simbolik dari background foto ini tidak dipahami atau tidak disadari oleh pelaku selfie di lokasi bencana. Mereka mengekspose wajahnya, padahal publik tidak butuh, kecuali ada yang baru yang ingin ditunjukkan dari wajahnya. Konsekuensinya, penderitaan yang direpresentasikan oleh background foto hanya menjadi aksesori dari wajah yang tak penting.
Akhirnya, pesan yang ditangkap publik bukan eksistensi fisik dirinya yang sedang berada di lokasi bencana melainkan ekspresi immoral yang diekspose dengan wajah tanpa rasa bersalah. Selfie bencana menjadi kutukan moral sosial di masyarakat kita yang sebelumnya telah menerima selfie sebagai perlaku baru yang normal. (Firdaus).