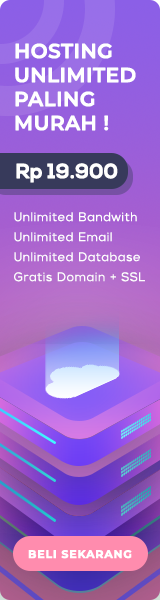BERBAGI News – Siang yang berubah menjadi neraka. Jantung gadis Rotterdam itu seolah ditancapi ribuan jarum. Ia mendadak lunglai. Tangannya gemetar. Pelahan ia menggeser letak duduknya, bersandar di tiang berugaq.
Ia menatap sosok di hadapannya yang nampak tenang-tenang saja, masih belum usai menikmati hidangan. Sikap pemuda itu membuat dadanya disesaki amarah dan kebencian. Tidak sadarkah ia dengan ucapan yang baru saja dilontarkannya? Ucapan itu membuatnya tiba-tiba merasa tak mengenal pemuda itu. Apakah sikap yang akan ditunjukkannya sekarang kepada pemuda yang ia anggap tak berperasaan itu? Menangis, marah, atau meninggalkannya tanpa berkata-kata?
Ia raih gelas yang tergeletak di lantai berugaq. Kobaran murka menghasutnya melemparkan benda itu ke wajah pemuda di depannya. Tetapi bisikan lain mencegahnya bertindak gegabah. Ia mesti menunjukkan kedewasaan dan harga dirinya. Ia berusaha menekan emosi, dan memulai bicara.
“Jangan artikan jatuhnya gelas ini lantaran saya kaget mendengar kata-katamu. Saya sama sekali tidak terkejut. Saya turuti keinginanmu. Kita akhiri hubungan ini. Dan silakan pergi dari hadapan saya sekarang juga,” gadis itu berusaha menampakkan diri tegar. Namun bendungan air mata itu kini tak mampu bertahan lagi. Ia menyembunyikan wajahnya, berpaling ke arah sungai. Gemercik alir Kali Jangkok kini berubah menjadi nyanyian pilu. Sungai air mata yang mengalirkan keperihan. Dinding hatinya seolah tersayat-sayat tajamnya sembilu.
Ahmad mengangkat wajahnya. Setelah meneguk habis air di gelasnya, ia menjawab gadis itu.
“Begitu mudahnya kamu berprasangka. Padahal kalimat saya belum selesai,” katanya tenang, “Saya memang akan pergi. Saya akan pergi menemui keluarga saya, meminta mereka datang ke mari. Datang meminangmu. Itu sebabnya hubungan yang sekarang ini kita akhiri, untuk membuat hubungan yang baru.”
Keterkejutan baru dirasakan gadis itu. Ia seperti tak yakin dengan pendengarannya. Ia merasakan sesuatu keadaan beralih tanpa transisi, seperti gelap yang tiba-tiba berubah terang yang membuatnya silau. Seperti panas terik yang mendadak ditumpas guyuran hujan. Bongkahan campur-aduk kekecewaan, amarah, kepedihan, dan frustasi itu tiba-tiba mencair, sehingga ia tak dapat menyembunyikan perasaannya. Ia menghambur, melompat ke pangkuan pemuda itu.
“Sekarang baru saya terkejut, Ahmad.”
Pemuda itu tak sempat menghindar. Ia rebah terlentang. Tubuh gadis itu menindihnya. Air mata sang gadis yang sempat tercurah itu kini menempel di keningnya. Wajah bertemu wajah.
“Sudah, Cornelia, sudah.”
Suara Ahmad menyadarkan gadis itu.
“Kamu bikin saya gemas. Kamu permainkan perasaan saya, Ahmad.”
Rabiyah tiba-tiba muncul. Perempuan itu menganga terheran-heran.
“Yaok, ye kembek kanak-kanak ne? Teboye sik dengan laun (lho, ngapain anak-anak ini. Dilihat orang nanti).”
Cornelia melepas himpitannya. Ia bangkit, memandang Rabiyah dengan tersipu-sipu. Tapi Rabiyah kembali ke dalam rumah.
“Kenapa saya jadi lapar sekarang?” ucap gadis itu.
“Makanlah. Kenapa dari tadi tidak makan?”
“Kamu bikin saya tadi hilang selera. Sekarang saya mau makan, tapi harus kamu suapin.”
“Kamu memang seperti anak kecil. Benar kata Rabiyah. Besok-besok saya akan repot menggendongmu, memandikanmu, menyuapimu,” kata Ahmad. Ia memulai menyuapi gadis itu.
“Kamu keberatan?”
“Jika itu memang kamu sukai, saya akan lakukan untukmu.”
“Dengan senang hati?”
“Tentu, dengan senang hati.”
“Kamu juga tidak boleh jauh-jauh setiap malam. Kamu harus bisa membuat saya sampai tertidur.”
“Saya akan mendongeng untukmu sambil mengusap-usap rambutmu.”
“Benarkah?”
“Benar. Kamu akan segera terlelap.”
“Lalu kalau saya sudah tertidur?”
“Saya pelan-pelan buka pintu.”
“Ke mana?”
“Ke luar, ngelayap.”
“Hah? Enak saja. Kalau begitu biar saya saja yang bikin kamu cepat tidur. Awas, kalau kamu nanti berani ke luar malam-malam sendirian.”
“Tambah nasinya lagi, ya?”
“Cukup, Ahmad,” gadis itu meneguk air lalu mengambil serbet, menyeka bibirnya. “Kapan keluargamu akan datang?”
“Dalam minggu ini.”
“Kenapa saat Willem masih di sini kamu tidak membicarakan rencana ini?”
“Waktu di pelabuhan tempo hari saya sudah sampaikan kepadanya. Saya hanya ingin restunya.”
“Dia merestui?”
“Alhamdulillah.”
“Apa yang saya siapkan kalau keluargamu datang nanti?”
“Tidak usah repot-repot. Mereka hanya sebentar, membicarakan waktu pelaksanaan ijab kabul.”
“Ahmad, kita tinggal di mana kalau sudah menikah? Apa di rumah Willem ini?”
“Kita tinggal di atas awan.”
“Saya serius, Ahmad.”
“Yang pasti kita tetap di Ampenan.”
“Kita akan tetap tinggal dengan inaq. Kalau kita punya anak, dia ikut mengasuhnya.”
“Kalau kamu sudah punya anak, kamu tidak dipanggil noni lagi.
“Dipanggil apa?”
“Inaq.”
“Tidak masalah. Yang penting kamu tetap panggil nama saya yang sebenarnya. Sesekali panggil, Cinta.”
Mereka terus bercengkerama. Dari arah jembatan, sepasang mata sipit sejak tadi mengawasi mereka.
*
Dua hari berikutnya beberapa utusan menemui Cornelia.
Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan. Mereka akan menikah pada pertengahan Juni mendatang. Dalam mempersiapkan perhelatan itu, keluarga Ahmad memberi waktu kepada Cornelia mengabari kerabatnya.
Tetapi ke mana kabar itu dialamatkan, apakah akan sampai? Jika pun sampai, apakah keluarganya bisa datang menghadiri? Gadis itu ragu. Hari itu, di Kalijati, Jawa Barat, 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh berunding dengan Panglima Tertinggi Balatentara Dai Nippon Jenderal Imamura. Perundingan yang secara resmi berakhir dengan pernyataan resmi: Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang! Secara resmi pula, hari itu Dai Nippon telah menduduki Pulau Jawa.
Cornelia mengeluh. Pikirannya membayangkan buruknya keadaan di Jawa setelah Belanda bertekuk lutut. (Bersambung/ Buyung Sutan Muhlis)